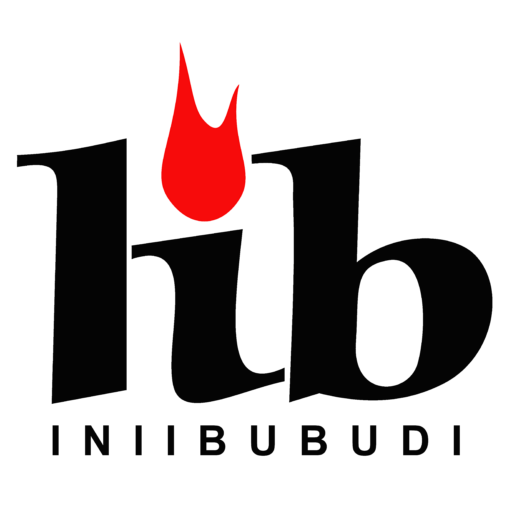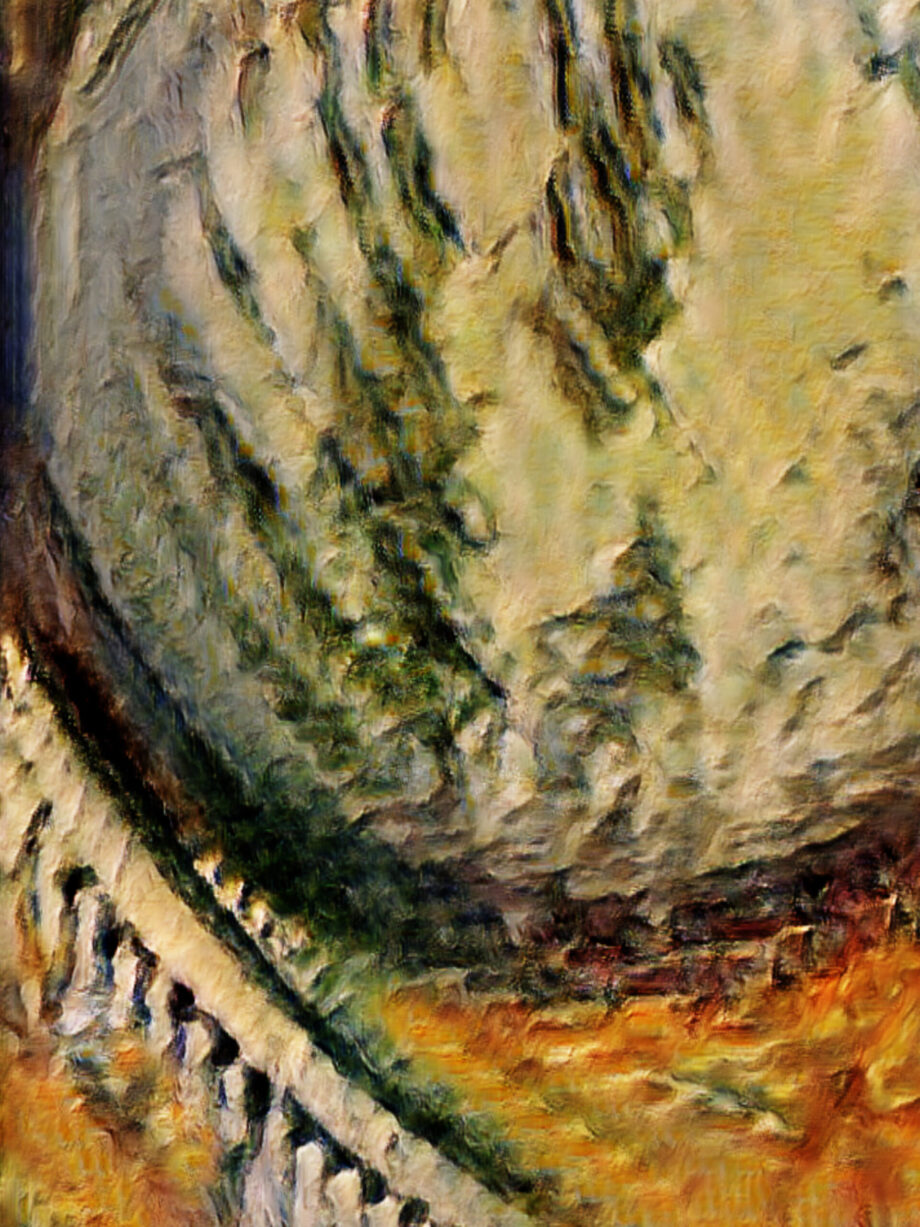Cerpen: Imam Khanafi
Fi berjalan di trotoar, menyusuri jalanan kota yang basah oleh sisa hujan. Ia berusaha mengindera segala sesuatu seperti seorang fenomenolog: merasakan hembusan angin, mencermati pantulan lampu di aspal, mendengarkan langkah-langkah asing yang berbaur dengan suara hatinya sendiri. Namun, realitas tak pernah benar-benar murni dalam kesadarannya. Selalu ada bias, selalu ada yang menyela—dan itu adalah Re.
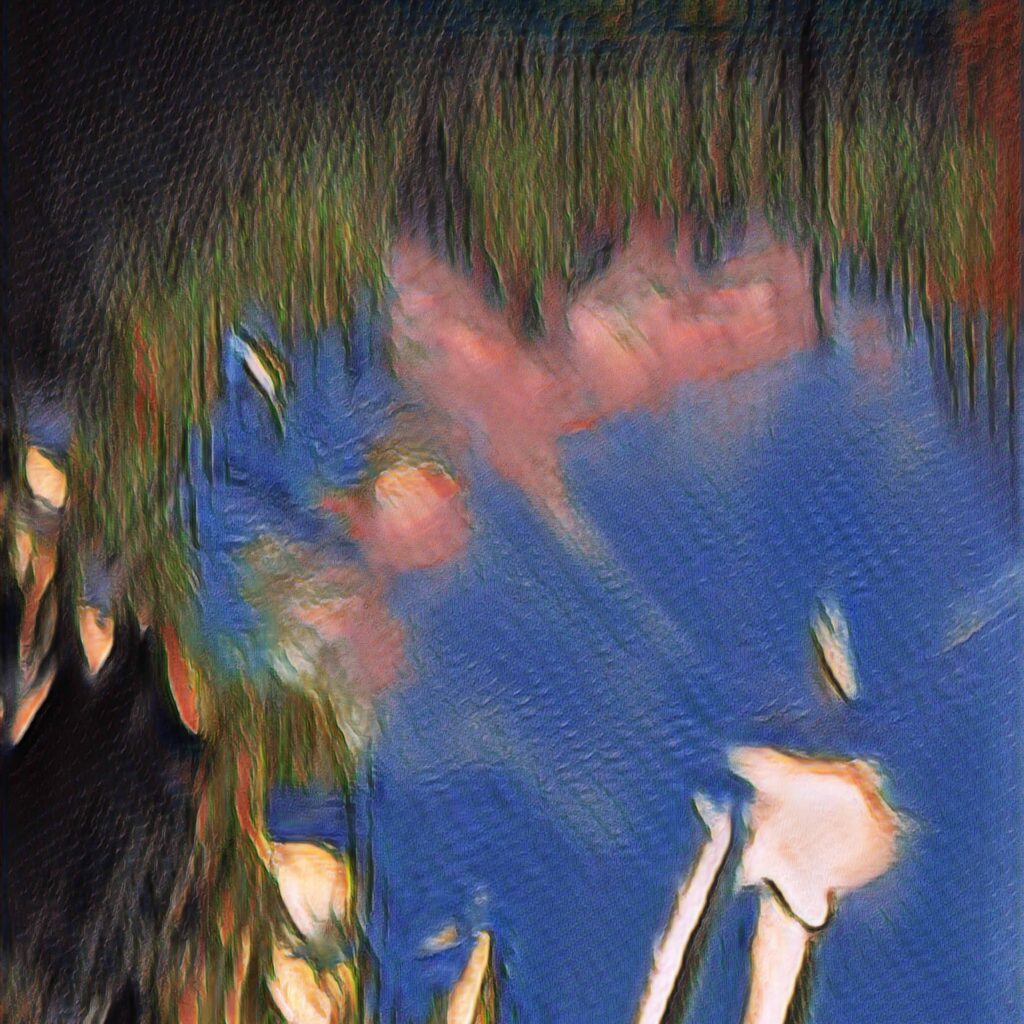
Kesadarannya tentang dunia selalu terdistorsi oleh satu nama. Fenomenologi mengajarkan bahwa pengalaman harus dihayati dalam bentuk yang paling esensial, tapi bagaimana mungkin jika setiap fenomena selalu berkelindan dengan sosok yang absen?
Ia tak pernah bisa sekadar melihat air yang menggenang tanpa melihat refleksi kenangan, tak bisa mencium aroma kopi tanpa membayangkan diskusi panjang yang dulu mereka jalani. Ia gagal menjadi fenomenolog karena dunia tak pernah bisa ia alami tanpa Re.
Fi menunduk, menatap bayangannya sendiri di genangan air. “Re,” bisiknya. Kata itu mengendap di tenggorokannya seperti mantra, mengalir lebih sering daripada doa. Fenomenologi gagal di tubuhnya, karena alih-alih menemukan hakikat sesuatu sebagaimana adanya, ia justru terus-menerus menemukan Re dalam segala sesuatu. Apakah itu berarti dirinya sendiri tak pernah benar-benar ada tanpa Re?
***
Fi terus berjalan di trotoar, menyusuri jalanan kota Kudus yang basah oleh sisa hujan. Lampu-lampu kendaraan memantul di aspal hitam, seperti bintang-bintang jatuh yang tersesat di bumi. Angin malam mengelus pipinya, membawa suara langkah-langkah orang-orang yang tidak ia kenal, tetapi keberadaannya entah mengapa terasa akrab.
Ia menunduk, menatap bayangannya sendiri di genangan air. “Re,” bisiknya.
Nama itu. Nama yang tak pernah habis ia ulang. Nama yang menjadi zikirnya, lebih sering daripada ia menyebut nama Tuhan dalam doa. Ada yang salah dengan itu? Bukankah dalam cinta, nama kekasih bisa menjadi jalan menuju ketuhanan? Plato mengatakan cinta adalah jembatan menuju ide tertinggi. Maka, menyebut Re—bukankah itu juga semacam pencarian keabadian?
Fi menghela napas. “Ah, filsafat terlalu banyak bermain di kepalaku.”
Ia ingat kata-kata Kierkegaard, bahwa kerinduan adalah penyakit sekaligus obat. Ia mengidapnya, akut. Tapi ia juga menikmatinya. Bukankah ada kenikmatan dalam rasa sakit yang kau tahu akan terus kau pelihara? Hanya dengan merindu, ia merasa tetap dekat dengan Re.
Di antara gemuruh mesin dan langkah kaki pejalan malam, Fi berbicara dengan dirinya sendiri. “Jika aku adalah subjek dalam cogito Descartes, maka aku rindu, maka aku ada.”
Mungkin itu sebabnya ia tak ingin melupakan Re. Bukan hanya karena cinta, tapi karena dalam menyebut namanya, ia menemukan keberadaannya sendiri. Tanpa Re, apakah ia masih ada?
Fi memejamkan mata. Angin membawa aroma tanah basah dan kopi dari kedai pinggir jalan. Andai Re ada di sini, mereka pasti sudah duduk bersama, mendiskusikan Sartre dan eksistensialisme, atau mungkin hanya diam, menikmati absurditas dunia sebagaimana Camus mengajarkan.
“Tapi Re tidak di sini,” gumamnya.
Mungkin ini yang dimaksud Hegel sebagai dialektika. Ada tesis: Fi dan Re bersama. Ada antitesis: Fi dan Re terpisah. Maka, apa sintesisnya? Apakah ia harus berhenti merindukan, atau justru menerima bahwa merindu adalah esensi dari keberadaan?
Fi kembali menyebut nama itu, pelan, hampir seperti doa. “Re.”
Apa kabarnya di sana? Apakah Re juga merindukannya? Ataukah ia hanya sebutir debu dalam sistem pemikiran perempuan itu, sesuatu yang bisa ditiup angin begitu saja?
Tidak. Itu tidak mungkin.
Fi percaya pada konsep intersubjektivitas Husserl. Jika ia merasakan sesuatu yang begitu dalam, pastilah ada resonansi di seberang sana. Rindu bukanlah monolog, ia adalah dialog yang tak terdengar.
Langkahnya terhenti di depan sebuah bangku taman. Ia duduk, membiarkan pikirannya mengembara lebih jauh.
“Re, andai aku bisa mendengar suaramu sekarang.”
Sejenak, dunia terasa hening. Seakan-akan semesta sedang mempertimbangkan permohonannya. Lalu, ponselnya bergetar.
Sebuah pesan muncul. Dari Re.
***
Fi menatap layar ponselnya, membaca pesan dari Re berulang kali. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah ini yang dimaksud Jung sebagai sinkronisitas—sebuah kebetulan yang terlalu bermakna untuk disebut kebetulan? Ataukah ini sekadar bias kognitif yang mempermainkan harapannya?
Tapi tidak, ia ingin percaya pada Levinas, bahwa keberadaan Re dalam pikirannya bukan sekadar ilusi solipsistik. Ada wajah, ada kehadiran, ada tanggung jawab eksistensial dalam merindukan seseorang. Maka, rindu bukan hanya soal subjektivitas, melainkan hubungan etis antara dua jiwa yang saling merasakan, meski di ruang dan waktu yang terpisah.
“Lalu, Fi,” ia berbicara dengan dirinya sendiri, “apa yang sebenarnya kau cari dalam cinta ini?” Ia ingin menjawabnya secara rasional, tapi cinta selalu menolak kategorisasi Aristotelian yang jelas. Jika cinta hanyalah bentuk lain dari kehendak seperti yang dikatakan Schopenhauer, maka ia hanyalah makhluk yang diperbudak oleh dorongan biologis untuk mencari kepenuhan.
Tapi jika cinta adalah pilihan bebas seperti yang diyakini Sartre, maka ia bertanggung jawab penuh atas ketergantungannya pada Re. Lantas, di mana letak kebebasannya? Apakah ia memilih untuk mencintai Re, ataukah cinta itu datang begitu saja, mengalir tanpa bisa dihentikan?
“Mungkin aku hanyalah seorang absurdis yang gagal,” gumamnya. Camus mengajarkan bahwa manusia harus menerima absurditas kehidupan tanpa mencari makna absolut. Tapi bagaimana jika absurditas itu justru melahirkan makna? Bukankah setiap kali ia menyebut nama Re, ia menemukan dirinya sendiri?
Jika Kierkegaard benar bahwa cinta adalah lompatan iman, maka ia telah melompat terlalu jauh tanpa peduli apakah ada tanah di bawahnya. Fi tertawa kecil, bukan karena bahagia, tetapi karena menyadari betapa ironisnya cinta yang ia jalani. Ia ingin bebas, tapi justru menjadikan Re sebagai pusat orbitnya.
Fi akhirnya membalas pesan itu dengan tangan gemetar. Pesan biasa, hanya ucapan terimakasih dari Re. Heidegger berkata bahwa eksistensi sejati adalah tentang keterlemparan ke dunia, dan mungkin cinta adalah bentuk keterlemparan yang paling membingungkan. Maka, ia menerima keterlemparannya, menerima bahwa dirinya adalah fenomenolog yang gagal, menerima bahwa menyebut nama Re adalah satu-satunya cara ia merasa masih ada. (*)

Imam Khanafi
Penulis tinggal di Kudus, aktif di Phos Zine sastra. Sedang mendalami fenomenologi, khususnya pemikiran Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, dan Jean-Paul Sartre.