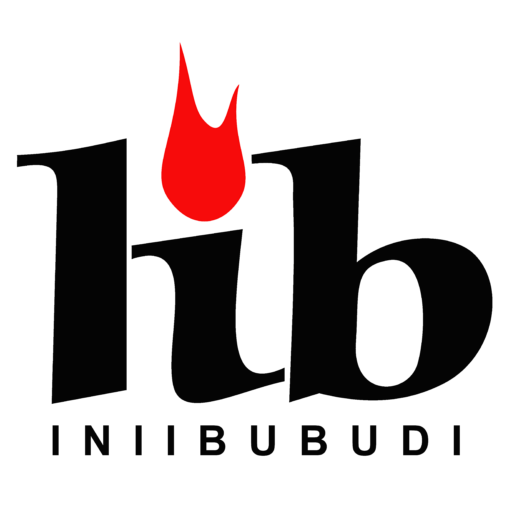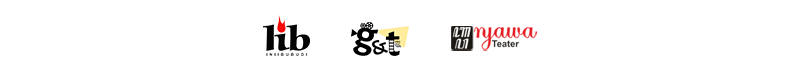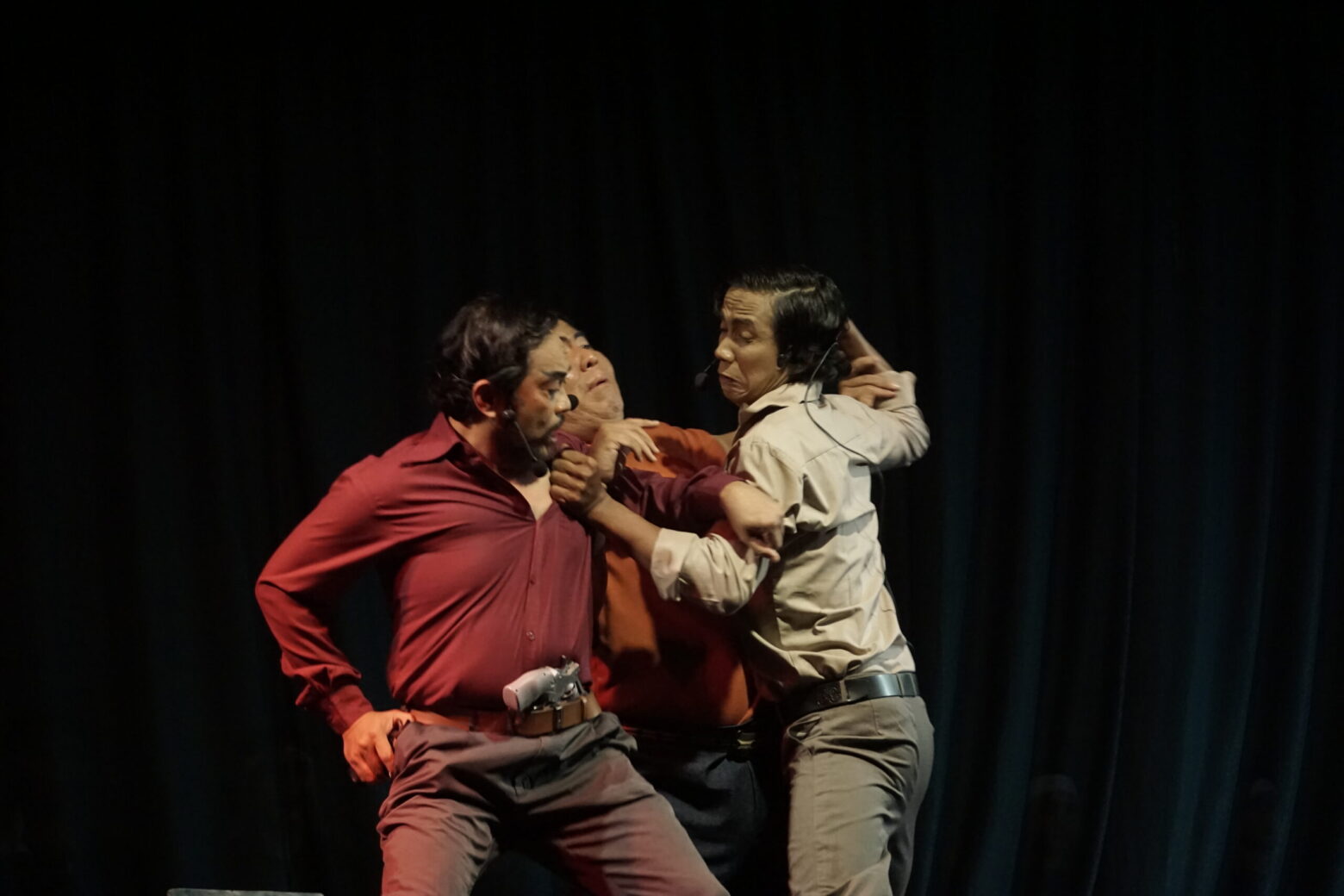Esai: Djoko Subinarto
DUNIA telah berubah secara radikal dalam dua dekade terakhir. Teknologi digital bukan hanya menciptakan cara-cara baru untuk berkomunikasi, tetapi juga mengubah cara manusia mencatat jejak kehidupannya. Di tengah ledakan informasi, sastra menemukan rumah baru yang tak berbentuk berupa ruang siber.
Dulu, tulisan tangan disimpan rapi dalam laci kayu atau lemari arsip. Manuskrip menjadi pusaka yang diwariskan lintas generasi, disimpan dalam kondisi khusus di perpustakaan atau museum. Kini, tulisan digital tersebar dalam bentuk unggahan media sosial, dokumen daring, atau e-book yang bisa diakses siapa saja, kapan saja. Namun justru karena ketersebarannya, keabadiannya jadi tanda tanya besar.
Dalam format digital, sastra seolah memperoleh janji keabadian. Tak lagi terbatas ruang dan waktu, karya dapat diunggah, disalin, dan disebarluaskan dalam hitungan detik. Tetapi, justru di balik kemudahan ini tersembunyi paradoks, yakni semakin luas jangkauan sebuah karya, semakin besar pula kemungkinan ia terlupakan di antara lautan konten. Karya kita bisa lenyap tanpa jejak, bukan karena dihancurkan, melainkan karena tak ditemukan.
Jujur saja, sastra digital membuka peluang luar biasa dalam penyebaran gagasan. Dari cerpen hingga puisi, dari esai hingga novel, semua bisa hadir di layar gawai. Tetapi, justru di titik inilah muncul ancaman berupa karya-karya yang tidak dikurasi, tidak terdokumentasi dengan baik, dan bisa lenyap begitu saja.
Ketika semua orang bisa menulis dan menerbitkan secara instan, perhatian publik menjadi sumber daya langka. Di sisi lain, algoritma media sosial bekerja seperti pintu gerbang yang menentukan mana yang layak tampil dan mana yang dikubur dalam diam.
Dalam dunia yang digerakkan algoritma, karya sastra kerap direduksi menjadi komoditas visual. Judul yang mencolok, kutipan yang memancing klik, menjadi nilai tukar utama. Kita berhadapan dengan dunia yang lebih menghargai keterlihatan dibanding makna.
Sejarah mencatat, banyak karya besar lahir dalam kesunyian, tak dikenal luas di zamannya. Shakespeare pun sempat luput dari perhatian hingga penemuan ulang oleh generasi berikutnya. Bayangkan jika karya-karya seperti itu hanya hidup di media sosial yang unggahannya menghilang dalam 24 jam. Bisakah mereka bertahan?
Platform digital seperti Instagram Stories, TikTok, dan Threads menjanjikan kecepatan dan keterlibatan. Meski begitu, mereka tidak dirancang untuk pelestarian. Tak ada katalog, tak ada indeks, tak ada sistem klasifikasi seperti di perpustakaan konvensional. Akibatnya, karya yang lahir di ruang ini lebih rentan terhadap pelupaan.
Di perpustakaan, kita tahu bagaimana menemukan karya sastra melalui kode, klasifikasi, dan katalog. Di ranah digital, semuanya mengandalkan pencarian dan tautan. Jika tautan mati, atau mesin pencari berubah algoritma, maka akses pun terputus. Kita hidup dalam sistem dokumentasi yang sebenarnya rapuh.
Rapuh bukan hanya karena teknologi, tetapi juga karena kebiasaan manusia modern. Kita membaca cepat, menyimpan sebentar, lalu pindah ke hal lain. Ini menciptakan budaya ingatan pendek di mana karya, tak peduli seberapa dalam atau indah, segera ditinggalkan setelah viralitasnya menurun.
Analisis kontemporer, seperti riset di Internet Archive, menunjukkan bahwa sekitar 50 persen tautan dalam domain mendalam (deep web links) sudah tidak aktif dalam waktu 1,5 hingga 2,5 tahun setelah diterbitkan. Rata-rata masa hidup halaman web saat ini berkisar antara 1 hingga 2 tahun, tergantung jenis dan tingkat perawatannya. Bandingkan dengan naskah kuna seperti Epic of Gilgamesh yang bertahan lebih dari 4000 tahun dalam bentuk lempeng tanah liat.
Ironinya, semakin canggih teknologi kita, umur teks jadi lebih pendek. Kita punya kemampuan menyimpan terabyte data, tapi tanpa sistem pelestarian, semua bisa lenyap seperti pasir di pantai. Karya yang kita anggap penting hari ini bisa jadi tak dikenali esok hari karena perubahan format atau platform.
Maka, dalam hal ini, persoalan kita bergeser dari “siapa pembaca kita hari ini” menjadi “bagaimana agar pesan kita tetap bisa dimengerti esok nanti.” Ini bukan soal prediksi, tapi soal kesadaran akan perubahan dan kebutuhan untuk mengarsipkan secara bijak.
Pada titik inilah bidang digital humanities bisa muncul sebagai jembatan. Ia memadukan ilmu teknologi, perpustakaan, dan kesusastraan untuk menciptakan sistem pelestarian yang tidak hanya menyimpan data, tapi juga konteks dan makna di baliknya.
Salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah emulasi, yakni menjaga sistem lama agar tetap bisa dijalankan di masa depan. Dengan ini, sebuah puisi interaktif yang dibuat dengan Flash pada tahun 2005 masih bisa dibaca di tahun 2050, jika perangkat lunaknya bisa ditiru.
Tanpa pendekatan semacam itu, kita akan kehilangan banyak karya yang unik. Pasalnya, platform bisa tutup, software bisa kadaluarsa, dan karya pun lenyap tanpa bisa dibuka kembali. Ini bukan sekadar kehilangan teks, tapi juga kehilangan pengalaman membaca yang dirancang oleh penulis.
Maka, ketika kita menulis sastra digital, kita perlu berpikir lebih dari sekadar isi. Kita juga harus berpikir tentang bagaimana karya itu akan hidup: formatnya, distribusinya, dan kelangsungan teknologinya. Sebab, arsip bukan hanya kumpulan data, tapi juga struktur makna.
Dalam teori informasi Claude Shannon, dikenal konsep signal-to-noise ratio, yaitu perbandingan antara pesan bermakna dan gangguan. Sastra digital hidup di tengah kebisingan luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana tetap menjadi sinyal, bukan noise.
Karya yang kuat akan selalu menemukan jalannya. Namun ia butuh sistem pendukung — kurator, pustakawan digital, dan pembaca kritis — yang bersedia menjaga dan membacanya terus-menerus. Tanpa itu, bahkan karya terbaik pun bisa hilang tanpa jejak.
UNESCO dalam berbagai pernyataannya menekankan pentingnya pelestarian warisan digital, terutama karena pertumbuhan data sangat cepat dan risiko kehilangan informasi juga besar. Meskipun tidak menyebut angka spesifik bahwa 90 persen data tidak tersimpan secara sistematis, UNESCO memperingatkan bahwa sebagian besar data digital memang tidak dipertahankan dalam sistem pelestarian yang memadai. Artinya, risiko kehilangan makna kolektif sangat nyata dan semakin mendesak untuk dihadapi.
Jika kita menyadari besarnya risiko tersebut, maka sesungguhnya kita sedang membangun peradaban di atas fondasi digital yang rapuh. Layaknya mendirikan perpustakaan megah di atas pasir, semua tampak megah di permukaan, tetapi tidak memiliki landasan kokoh untuk bertahan dalam jangka panjang.
Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya kolektif lintas disiplin — penulis, akademisi, pustakawan, programer, hingga pembuat kebijakan — untuk bersama-sama mengarsipkan, mengklasifikasi, dan merawat karya digital seperti halnya kita menjaga prasasti kuno. Sebab, warisan budaya tidak cukup disimpan. Ia harus dijaga agar tetap hidup dan bisa dibaca kembali oleh masa depan.
Viralitas sering kali menipu. Ia memberi ilusi bahwa karya kita penting karena disukai banyak orang. Padahal, banyak warisan budaya sejati justru lahir dan tumbuh dalam ruang sunyi, dibaca ulang oleh sedikit orang yang serius.
Karya Chairil Anwar, Rendra, atau bahkan Pramoedya, tidak serta merta langsung populer. Mereka bertahan karena dibaca ulang, ditafsir ulang, dan didokumentasikan. Dan kita wajib bertanya pula ihwa siapa yang akan membaca ulang karya-karya digital kita nanti.
Platform seperti Facebook, Wattpad, Medium — semuanya bukan milik kita. Mereka bisa gulung tikar, mengubah kebijakan, atau menghapus data kapan saja. Menaruh seluruh warisan budaya di platform ini seperti menulis di atas air.
Di sinilah peran lembaga arsip dan perpustakaan digital menjadi krusial. Situs seperti Internet Archive, Perpustakaan Nasional Digital Indonesia, atau Project Gutenberg memberi ruang bagi karya digital untuk tetap hidup dalam jangka panjang.
Namun, jumlahnya belum cukup. Dibutuhkan kesadaran publik, kebijakan negara, dan kolaborasi komunitas untuk memperluas ruang pelestarian ini. Kita butuh tidak hanya pustakawan, tapi juga penulis yang sadar arsip.***
——————-

Djoko Subinarto
Esais dan kolumnis.