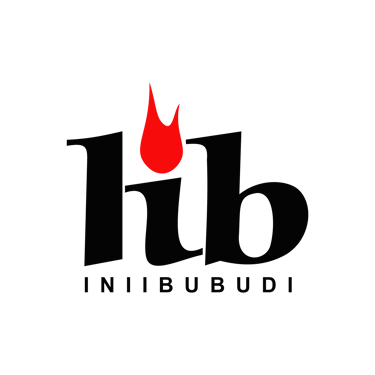Kapling
CERPEN
Karya: Yohanes Budi Utomo
12/1/2024
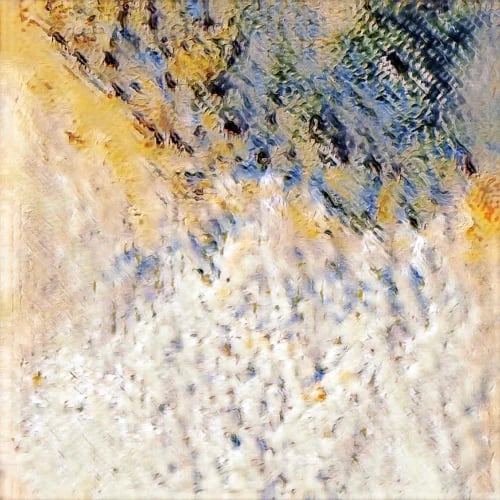

DI BALIK dinding ruang tamu, Mama terlihat bicara serius dengan seseorang di balik telepon. Aku, yang duduk di ruang tengah, terpaksa menguping.
“Kurangi dikit-lah?”
Mama menjawab, sambil terbatuk-batuk ringan, “Dua tujuh saya lepas dech!”
“Ya. Jangan segitu lah Ci. Kita kan sudah saling kenal. Masak segitunya. Itu pun tidak mereka pakai sekarang-sekarang ini,” kata suara di balik telepon. Sambil memohon-mohon, ia bicara lagi. “Berilah kelonggaran. Untuk apa mahal-mahal, tokh Cici belum butuh,” Katanya dengan nada membujuk.
“Kalau aku butuh sekarang, berarti aku sudah mati,” kata Mamaku.
“Hehe…, ya maaf, Ci,” Suara lelaki itu terkekeh.
“Begini saja. Aku kasih harga final, dan gak ada tawar menawar lagi. Lima puluh untuk dua kapling!” kata Mama lantang.
“Agh, Cici. Tidak bisa turun lagi ini Ci?”
“Sudah kubilang. Kalau bos-mu mau ya ambil. Kalau tidak. aku bisa jual lebih tinggi ke orang lain!” Tampaknya Mama berhasil membuat sang makelar tak bisa menawar lagi.
“Oke. Aku sampaikan nanti. Tapi, kalo Cici berubah pikiran, kabari aku saja.”
“Tidak ada lagi yang akan berubah!” Jawab Mama tegas.
“Oke. Oke. Btw. Boleh aku tanya sesuatu Ci?” katanya lagi.
“Apa?”
“Kenapa Cici tiba-tiba ingin menjualnya? Bukannya dulu tak mudah mendapatkannya. Kapling yang Cici punya itu tempatnya sangat strategis lho. Apa nggak sayang kalau dijual?”
“Sudahlah. Tidak perlu diungkit lagi. Hidup harus terus berjalan,” kata Mama.
Wajah Mama berubah sendu. Masih dengan telepon yang menempel di telinganya, Mama keluar rumah. Sejak itulah, aku tidak lagi bisa mendengar apa yang dibicarakan Mama dengan seseorang yang menelponnya.
Hanya sesekali, aku mendengar Mama mengatakan “tidak” dengan kerasnya.
Aku masih pura-pura menelungkupkan kepalaku pada sebuah buku. Sedari tadi, belum berpindah halaman. Aku belum paham benar sedang bisnis apakah Mama sekarang. Setahuku, Mama tak punya kerja sampingan lain. Tapi, tidak tahu juga, bisa jadi Mama melakukan hal lain tanpa sepengetahuanku. Tapi, kenapa Mama bicara harga. Sejak kapan Mama menjadi pebisnis. Jika iya, apa yang Mama jual? Agh. Pikiranku mulai menggelandang ke mana-mana. Aku takut berpikir lebih jauh tentang Mama. Aku sangat menghormati sekaligus menyayanginya.
Sewaktu kecil, Mama pernah menyelamatkanku dari Papa. Kata Mama, sejak kejadian memalukan itu, Papa tak pernah berhenti menginginkanku. Tetapi Mama selalu bisa menggagalkannya. Awal perkara, Mama memergoki Papa sedang bersama seorang wanita lain. Dan, tanpa ampun lagi, Mama mengusir Papa dari rumah. Tentu saja, Papa marah.
“Bagaimana mungkin kau mengusirku Lusi. Aku bangun rumah ini dengan kerja keras, untuk kita, untuk anak-anak kita!” kata Papa.
Mama tak bergeming. “Kalau kau merasa kerja keras membangun rumah ini, seharusnya kau tak nodai rumah ini dengan polah tingkahmu yang memuakkan itu. Ambillah sebisa barang yang bisa kau bawa. Tapi, jangan pernah coba-coba bawa anakku!”
Itulah akhir ceritaku dengan Papa. Pertengkaran hebat dengan Mama, membuat Papa merasa terdesak, sekaligus bersalah. Sejak itulah, Papa tak pernah lagi pulang ke rumah.
Padahal, seburuk-buruknya Papa, ia tetaplah Papaku. Meski memang Papa terkadang menjengkelkan, sangat menjengkelkan. Suatu malam, aku dan Mama dengan sengaja menunggu Papa pulang kerja. Hari itu, tepat ulang tahun pernikahan Papa dan Mama. Dan, tak biasanya Mama telah siapkan masakan istimewa untuk merayakan ulang tahun secara sederhana.
Biasanya jam delapan malam, Papa sudah sampai rumah. Tapi, ini sudah menjelang jam sepuluh, Papa tak kunjung pulang. Mama sudah tak tenang. Bawaannya emosi terus. Mau tidur tak nyenyak. Mau makan tak sampai hati.
Mama hanya bilang, “Sabar ya, Nak. Sebentar lagi Papa pasti pulang.” Meski sebenarnya aku tahu, Mama berbohong lagi. Papa pasti pulang dini hari. Papa pasti lupa hari ulang tahun pernikahannya dengan Mama. Benar saja. Sampai jam dua belas malam, menjelang dini hari, aku dan Mama tak kuasa menahan kantuk. Kami akhirnya tertidur di sofa ruang tamu. Hingga, sebuah suara mengagetkan kami semua.
“Lusi. Buka pintunya. Ini aku, Lus!” suara Papa memanggil-manggil Mama. Saat mendengar pintu diketuk, Mama langsung melihat jam dinding: jam empat pagi.
Mama tak segera bergegas membuka pintu. Aku pun segera dibangunkan untuk segera pindah ke kamar tidur. Setengah sadar, aku menurut apa kata Mama.
Sejurus kemudian, Mama pergi ke belakang dan kembali lagi dengan membawa segayung air. Mama pun lalu membuka pintu.
“Rasakan ini. Upah keluyuran sampai pagi ya pantesnya begini!” Kata Mama sambil mengguyurkan air ke muka Papa. Papa gelagapan. Tapi karena Papa setengah sadar oleh minuman keras, segera menelungkupkan kepalanya dan mendekap kaki Mama.
“Maafkan aku, Lus. Maafkan aku.”
Mama diam saja, sambil berupaya melepaskan kakinya dari pelukan Papa. “Kau tidak berperasaan. Aku dan Mei menunggumu semalaman. Tapi kau sama sekali tak peduli. Bahkan untuk ingat tanggal pernikahan kita saja, kau tak ingat.” Kata Mama emosional.
Aku yang sedari tadi mengintip dari balik pintu kamar, segera menutup pintu rapat-rapat, dan menangis sejadi-jadinya. Melihat Papa dan Mama bagaikan bumi langit. Aku belum mengerti, kenapa Papa melakukan itu semua pada Mama.
Yang pasti, aku tahu bahwa Mama adalah cinta mati Papa. Begitulah Papa bercerita suatu ketika. Sebelum sering terjadi huru hara di rumah, Papa sering mengajakku bersepeda keliling kompleks. Saat itulah, aku melihat sosok Papa yang sangat keren. Hampir semua tetanggaku mengenal Papa. Sepanjang perjalanan, Papa tak henti-hentinya tersenyum, menyalami, dan menyapa orang-orang yang berpapasan dengan Papa.
Kerennya lagi, di sepanjang perjalanan Papa selalu bisa membuatku tertawa. Persis saat di tengah taman, Papa membuat atraksi jumping dengan sepedanya. Kontan saja, aku bertepuk tangan, “Papa memang kereeen!” Kataku sambil memberikan dua jempol.
Papa mendekatiku, dan membisikkan sesuatu. “Kamu persis seperti Mamamu. Aku sayang kamu, juga Mamamu.” Aku hanya tersenyum, tersanjung dengan ucapan terindah yang pernah kudengar dari Papa.
Papa bicara lagi. “Kamu tahu Mei-Yin. Cintaku pada Mamamu adalah sepanjang hidupku hingga matiku. Mungkin kamu belum paham sekarang. Kelak, seiring waktu, kamu akan tahu makna sebenarnya.” Lagi-lagi aku hanya tersenyum.
Papa melanjutkan, “Karena itu. Papa dan Mama sepakat membeli kapling di atas bukit itu. Itulah bukti cinta Papa pada Mamamu.” Wajahku datar.
“Pada saatnya Papa dan Mama akan pergi dari dunia ini. Di bukit itulah, nanti kami akan menyatukan rumah keabadian. Seperti cinta Papa kepada Mama yang abadi sepanjang masa.”
Namun, sejak peristiwa itu, tidak ada lagi kisah indahku dengan Papa. Ada satu ruang kosong di hatiku yang selalu siap menantikan pulangnya Papa. Entah sampai kapan.
***
Mama memanggilku, “Mei.” Aku mendekat, sambil kulipat bukuku, lalu kuletakkan di atas meja. “Ada apa, Ma?”
“Mei. Aku ingin bertanya satu hal padamu?”
“Ya, Ma.” Tidak biasanya Mama menjadi serius begini. Aku menunggu. Moga-moga ada penjelasan langsung dari Mama terkait dengan bisnis yang Mama sedang jalankan.
“Mei. Kamu tahu. Mama sekarang sedang jatuh. Pendapatan Mama sebagai guru privat mulai menyusut. Kalah saing dengan guru-guru privat online. Untuk bayar uang sekolahmu saja belum cukup.”
“Kalau Mama mau, Mei bisa berhenti sekolah, Ma! Mei akan kerja!”
Mama tersenyum, sambil mengelus kepalaku. “Tidak Mei. Satu-satunya warisan Mama yang paling berharga adalah pendidikan untukmu. Kamu tidak boleh berhenti sekolah. Karena itu, Mama minta satu hal padamu. Ijinkan Mama menjual kapling di bukit itu, Mei.”
“Tapi, Ma?”
“Mama tahu. Papamu juga punya hak atas kapling itu. Entah di mana sekarang Papamu. Mungkin saja, Papamu sengaja mewariskan kapling itu untukmu. Karenanya, aku minta ijin padamu, Mei.”
“Ma. Aku tak peduli dengan kapling itu, Ma. Yang kupedulikan hanya Mama dan Papa. Seandainya Papa ada di sini, tentu tidak akan serumit ini ya Ma.” Aku merengek.
“Kita tidak boleh cengeng seperti itu, Mei. Kamu harus kuat! Hidupmu masih panjang. Kapling itu memang tabungan masa depan Mama dan Papamu. Tetapi, hidup sekarang ini lebih penting dari semuanya. Ya sekolahmu dan hidupmu, Mei!”
“Aku tahu, Ma. Kira-kira, Papa ada di mana ya, Ma?”
Tiba-tiba, wajah Mama berubah. ”Jangan sebut lagi Papamu, Mei!” Tidak kusangka, Mama sedemikian marahnya. Aku mengangguk pelan, “Iya, Ma!”
Terdengar pintu rumah diketuk. Mama bergegas ke depan dan membuka pintu. Wajah Mama mendadak sumringah.
“Silakan masuk. Maaf, ruang tamunya berantakan,” kata Mama.
Seorang laki-laki setengah baya tampak mengangguk pelan. Perawakannya tinggi besar, persis seperti tuan-tuan besar zaman kumpeni di film-film perjuangan. Pakaiannya parlente, warna putih putih, kontras dengan kacamata hitamnya. Satu orang lagi, menyapa Mama dengan akrabnya. Tampaknya orang itu yang kemarin menelpon Mama. Dialah yang mencairkan suasana, dengan celetukan-celetukan yang mengundang kelucuan.
Mama mengawali pembicaraan dengan lebih serius, “Mm. Maaf. Sebelumnya terima kasih atas kedatangan Bapak. Mas Soni tadi mengabari kalau Bapak mau datang ke sini. Tapi, rupanya Bapak lebih cepat dari waktu yang disampaikan Mas Soni. Jadi, beginilah keadaannya, saya tidak bisa menyiapkan apa-apa.” Mama berbasa-basi.
Seseorang yang disebut Mas Soni hanya tertawa kecil. “Tidak apa Ci. Kebetulan tadi Bapak lagi ada acara di daerah sini. Sekalian saja mampir, he he…” Kata Soni.
“Oh. Begitu. Baiklah. Jadi, bagaimana Pak?” Kata Mama agak kikuk.
“Panggil saja, Herman!” kata pak Herman sambil menyodorkan tangannya ke Mama. Mama pun menyambutnya dengan hangat, “Lusi!”
Lagi-lagi Soni yang aktif menjawab, ”Iya Ci. Jadi. Bapak sudah setuju dengan harga penawaran yang Cici berikan tempo hari. Nanti Cici tinggal kasih nomor rekeningnya ke saya.”
“Oh, baiklah Mas. Nanti saya akan kirimkan nomornya,” kata Mama dengan lugasnya.
Herman menggeser tempat duduknya, sambil membetulkan kerah bajunya. “Lusi tidak perlu kuatir tentang harga. Saya sudah periksa lokasi kapling makam yang akan kamu jual.” Suaranya serak-serak berwibawa. Ia melanjutkan, “Saya sangat menyukai tempat itu. Jadi segera setelah ini, saya akan transfer!”
Raut muka Mama benar-benar sumringah. Mama menarik napas panjang. Napas kelegaan. Betapa tidak, minimal setelah ini, Mama akan terbebas dari hutang-hutang yang menjeratnya. Mama tersenyum. “Baik pak Herman. Terima kasih Bapak sudah cocok dengan harga penawaran saya. Mudah-mudahan, tempat itu pada nantinya akan menjadi berkah bagi Bapak dan keturunan Bapak...”
Sang tamu tersenyum kecil, “Termasuk keturunanmu juga, Lusi!”
Soni menimpali, “Ya Ci. Eh… begini Ci. Sebenarnya, bapak ini tidak sekadar ingin membeli kapling yang Cici tawarkan itu. Tapi... lebih dari itu, Ci!”
Raut muka Mama berubah. “Maksud, Mas Soni?”
Soni berpaling ke arah tuannya. “Mm. Begini Ci. Sebenarnya, pak Herman juga menawarkan beasiswa kepada Mei.”
Mama terperanjat. “Maksud pak Herman, Mei anak saya?”
Herman menyahut, “Benar Ibu. Saya dengar, tahun depan Mei masuk SMA. Jadi, kalau kamu membolehkan, saya akan bantu biaya sekolah Mei sampai selesai SMA-nya. Jika perlu, sampai Mei lulus sarjana.”
Mulut Mama tiba-tiba bungkam. Antara senang, heran, bahagia, dan khawatir bercampur jadi satu. Dengan beasiswa ini, tentu Mei bisa sekolah sampai tuntas. Mama menunduk. Apakah ini mimpi. Tidak terasa, Mama meneteskan air mata.
“Pak Herman. Saya menghargai maksud Bapak. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.”
Herman mengangguk-angguk dengan mulut tersenyum. Soni pun tak kalah senangnya.
“Hanya saja. Saya belum memahami dengan utuh, maksud sebenarnya dari pak Herman apa ya? Mm. Maksud saya. Saya tidak mau berutang budi seumur hidup, tanpa tahu bagaimana cara membalasnya.”
Soni menjawab dengan cepat, “Eh. Begini Ci. Sebenarnya…” Belum habis kalimat yang hendak diucapkan Soni, Herman segera menimpali. “Mm. Begini Lusi. Saya paham keraguanmu. Senyatanya, saya tulus membantu Mei. Saya hanya ingin Mei sekolah setinggi-tingginya.”
“Hanya itu…?” tanya Mama.
Soni dan Herman saling berpandangan.
“Oke. Oke. Begini Lusi…,” Sepertinya Herman tak bisa lagi berbasa-basi. “Harap kamu tidak marah atau berprasangka buruk terhadap saya. Niat saya hanya membantu. Tapi kalau kamu keberatan, tidak masalah. Yang pasti, saya hanya mengagumi kegigihanmu, berjuang mati-matian membesarkan Mei…”
“Saya makin bingung, pak Herman. Adakah penjelasan yang lebih terang benderang?”
“Sebenarnya, dua kapling yang akan saya beli itu adalah satu paket, untuk saya dan istri saya nanti. Sayangnya, sampai sekarang, Tuhan belum mendekatkan jodoh saya. Karena itu, jika Tuhan berkehendak, maka saya mau mempersunting kamu menjadi istriku.”
Buru-buru Herman menjelaskan lebih lanjut. “Tapi kalau kamu keberatan, tidak apa. Saya tetap akan memberikan apa yang menjadi tujuan awal saya. Kapling itu tetap saya beli. Mei tetap dapat beasiswa dari saya.”
Mama tertunduk. Ia seperti prajurit yang kalah perang. Pun pula seperti burung yang patah sayapnya, jatuh terkulai di tanah kering. Tak tahan lagi, Mama meneteskan air mata. Ia benar-benar marah pada keadaannya sekarang. Ia benar-benar jatuh di titik nadir. Sebagai seorang ibu, tidak ada yang lebih membahagiannya selain melihat anaknya sukses dan bahagia. Tapi…
“Mama..!” Tiba-tiba dari arah belakang, Mei mendekap Mamanya dengan hangat. “Aku sayang Mama!”
Lusi mendekap Mei dengan sekuatnya. “Mama juga sayang kamu, Nak!”
Mei berbisik manja, “Ma. Papa sudah pulang!”***
Sawangan, Depok 2024.
--------------------------
YOHANES BUDI UTOMO
Menulis Buku: Mengenal Jati Diri (2008); Tokoh Teater Indonesia (2010); Teater Tradisional Jawa (2010); Berpikir Positif (2011); Hidup Penuh Harapan (2012); Berani Tampil Beda (2012); Remaja Sehat Iman Kuat (2012); Bolehkah Aku Berpacaran (2012); Jelajah Alam (2017); Melawan Korupsi Dengan Kantin Kejujuran (2016, Penulis Terbaik Buku Non-Fiksi versi KPK-IKAPI); Indonesia Kaya dalam Keberagaman (Perpusnas, 2021, Kontributor); Menua Bersama Senja (Kumpulan Cerpen, 2024).