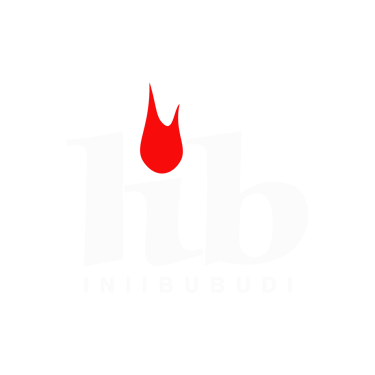Palsu: Puisi dan Pengakuan
ESAI
Oleh: Bandung Mawardi
7/1/2025

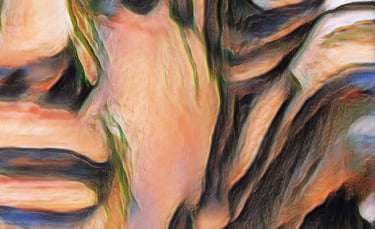
--------------------------
BANDUNG MAWARDI
Penulis dan Pedagang Buku Bekas.


POLITIK diawali miskin dan prihatin. Babak terpenting agar kemunculan tokoh berpolitik tak mendapat seribu curiga. Miskin itu penting. Hidup dengan keprihatinan sebelum jadi tokoh tenar di politik itu keharusan. Konon, penjelasan itu terdapa dalam rezim Orde Baru. Miskin menjadi takdir untuk mengerti dan memiliki kekuasaan.
Pada tahun-tahun menjelang keruntuhan rezim Orde Baru, para pengarang dan intelektual berani galak memberi kritik atas kemapanan bermajikan Soeharto. Indonesia dicap rusak dan berantakan. Tulisan-tulisan mengingatkan aib-aib politik “rajin” bermunculan.
Remy Sylado (1997) menggubah puisi berjudul “Sang Jurkam”. Kita mengingat sosok-sosok berpolitik selama masa Orde Baru. Biografi terbaca: Dia pemain politik/ Semasa kuliahnya miskin/ Ayahnya memperoleh upah harian/ dari pemilik kebun cengkih di Sonder/ tatkala tanaman itu masih primadona Sulut/ Ada rindu di hati yang membuatnya seperti disiksa/ bahwa besok jika dia kaya dari bermain politik/ dia akan mengurus jambulnya di salon/ memakai jas wol dan dasi sutra dari butik/ serta arloji emas berhiaskan berlian-berlian. Ia mengerti bila bermain politik mengharuskan jujur, bohong, sopan, gertak, dan lain-lain. Politik disadari sesak kepalsuan.
Sang Jurkam mendapat nasihat agar tak dikutuk Tuhan: Memang zaman ibarat sungai musim penghujan/ riaknya terus berubah berbuih sampai ke laut/ Di sana orang-orang mewakili peran-perannya/ antara kebaikan sepenuh hati dan setengah hati/ Di depan berpenampilan nabi/ di belakang berpenampilan babi/ Di depan alim beradab/ di belakang lalim biadab/ Apakah kau tidak sanggup melihat kebenaran/ yang kau sangka nyata itu/ sama seperti tahi, mubazir, dan busuk? Orang-orang mengalami hidup pada masa Orde Baru dan menjadi saksi kejatuhan rezim Orde Baru (1998) paham mengenai ulah kaum politik. Mereka tak wajib berpedoman kebenaran, kebaikan, ketulusan, dan keadilan.
Pengisahan mengandung kritik pun diajukan A Mustofa Bisri melalui puisi berjudul “PT Rekayasa Semesta”. Para pembaca mudah mengikuti cara kritik menggelitik oleh kiai dan pengarang asal Rembang. Puisi merekam situasi politik Orde Baru. Kita membaca: PT juga bersedia/ ikut merekayasa:/ pemilihan-pemilihan/ mulai dari pemilihan umum biasa/ pemilihan kepala desa/ hingga pemilihan ketua perkumpulan. Dulu, orang-orang mengetahui rezim Orde Baru itu “orde tipu-tipu”. Konon, segala perkara dapat dirampungkan dengan cara-cara melawan benar dan masuk akal.
Lakon masa lalu belum tamat meski Soeharto tak lagi berkuasa. Sekian cara dan siasat masih diselenggarakan dalam menghancurkan etika politik dan estetika kekuasaan. Mustofa Bisri melanjutkan: PT juga menerima:/ pesanan merekayasa/ pasien agar terus berobat hingga sekarat/ dokter agar menulis surat keterangan sakit atau sehat/ merekayasa hakim agar membebaskan terdakwa/ yang bersalah dan menghukum yang tak tahu apa-apa/ merekayasa terdakwa agar mengaku atau merogoh saku. Kini, kita mengingat masa Soeharto berkuasa sambil mesem sinis dan sedih. Konon, pelbagai ulah itu diwariskan sampai sekarang. Dua puisi cukup memberi peringatan agar masa lalu tak mendapat kesempatan berulang dan berlanjut.
Kita masih menemukan satu puisi mengiringi bobrok dan kejatuhan rezim Orde Baru. Agus R Sarjono memberi “Sajak Palsu.” Dulu, puisi itu dianggap menguak keburukan-keburukan telanjur lama bertumbuh di Indonesia. Puisi tetap sulit memberesi Indonesia. Puisi bukan “obat” atau “sulap” agar Indonesia bergirang.
Puisi digubah pada 1998. Kita membaca puisi sambil mengingat tahun bersejarah dan dampan terasakan sampai sekarang. Agus R Sarjono menulis: Masa sekolah/ masa demi masa sekolah berlalu, mereka pun lahir/ sebagai ekonom-ekonom palsu, ahli hukum palsu,/ ahli pertanian palsu, insinyur palsu. Sebagian/ menjadi guru, ilmuwan atau seniman palsu. Dengan gairah tinggi/ mereka menghambur ke tengah pembangunan palsu…. Puisi ramai diksi “palsu”. Kita maklum bila diberi judul “Sajak Palsu”. Di ujung, para pembaca membuktikan tentang “demokrasi palsu” tersaji di Indonesia, dari masa ke masa.
Masa lalu mengandung palsu-palsu. Orde Baru mengajarkan seribu palsu. Kita tetap mengingat masa lalu sambil menikmati lucu melalui pengakuan Mahbub Djunaidi (1980). Ia pernah ingin menjadi sarjana, tak peduli palsu atau asli. Penjelasan berlatar Orde Baru: “Di kantor mana pun, sarjana itu seperti kepingan meteor yang jadi pusat perhatian, ucapannya bertuah dan mudah naik pangkat tanpa memperhitungkan hasil kerjanya… Sarjana itu punya kelainan dibanding makhluk biasa, seolah-olah bukan lolos dari liang rahim, melainkan dari sela-sela batuan kalsit.” Keinginan dibatalkan gara-gara mengetahui susah-susah dalam kuliah.
Konon, masuk perguruan tinggi itu sulit melebihi sulit mendulang intan. Ongkos kuliah terlalu mahal. Predikat menjadi mahasiswa berakibat ruwet dan jantungan. Mahbub Djunaidi berkelakar: “Salah-salah buatan sebelum sampai jadi sarjana, saya sudah digotong orang ke makam umum.” Ia mengerti ada jalur atau siasat tetap menjadi sarjana palsu asal ada keberanian dan duit. Dulu, orang-orang “cepat” atau “tiba-tiba” menjadi sarjana. Mereka itu sarjana palsu berhasil bekerja di kantor-kantor pemerintahan Jakarta. Geger besar terjadi di Jakarta (1980) akibat pengusutan para sarjana palsu menjadi pegawai atau pejabat.
Segala buruk itu menjadi pertimbangan Mahbub Djunaidi berhenti menuruti keinginan menjadi sarjana: “Maka, sesudah merenung-renung, sesudah mandi di tujuh sumur, saya memilih tetap jadi penulis dan wartawan saja, habis perkara.” Ia mengerti: sarjana asli dan palsu tetap menanggungkan masalah-masalah berat di Indonesia. Begitu.(*)