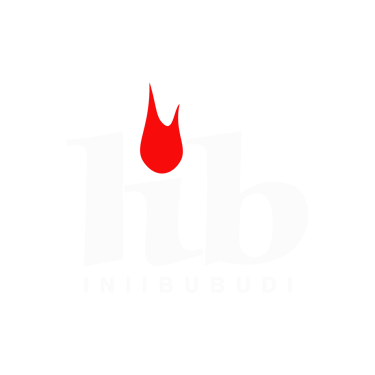Skeptisisme Sastra Inferior
ESAI
Oleh: Vito Prasetyo
8/1/2025


PRAMOEDYA ANANTA TOER pernah menuduh Hamka sebagai karya plagiat pada roman “Tenggelamnya Kapal Van der Wijk”. Roman ini menjiplak Sous les Tilleuls¹ karya Jean-Baptiste Alphonse Karr. Hingga kemudian Hamka mengatakan bahwa ia terpengaruh karya Jean-Baptiste Alphonse Karr beberapa tahun kemudian.
Chairil Anwar dikenal pernah melakukan penyaduran atau adaptasi dari karya sastra asing ke dalam sajaknya. Preludes for Memnon² karya Conrad Aiken adalah salah satu sajak yang diadaptasi oleh Chairil Anwar. Di sini, Chairil Anwar menyisipkan sentuhan pribadinya. Dan juga dalam sajak “Karawang-Bekasi”, Chairil Anwar dituduh melakukan plagiasi atas karya Archibald MacLeish bertajuk The Dead Young Soldiers³. Namun, H.B Jassin berpendapat dalam karya Chairil Anwar memiliki keunikan tersendiri, meski ada kemiripan.
Terhadap karya-karya sastra yang diadaptasi dari pengarang asli, terkadang menjadi anomali dalam sudut pandang berbeda. Tentu ada alasan bagi seorang pengarang untuk mengadaptasi terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Karena pada dasarnya, setiap pengarang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang digunakan sebagai cara untuk menulis. Hal ini karena pengarang juga dihantui oleh sikap keragu-raguan (skeptis) bagi karya yang dihasilkan; harus bagus meski ukurannya subjektif. Jangan-jangan karya mereka dianggap sebagai karya sastra inferior (bermutu rendah).
Menurut Jorge Luis Borges (1937), cara penulisan yang digunakan pengarang, disebut sebagai teknik menulis. Borges mengatakan, ada dua jenis tulisan yang dikenal. Pertama, mereka yang fokus utamanya adalah dengan teknik verbal. Dan yang kedua adalah penulis yang berfokus pada tindakan dan hasrat manusia. Ini seperti yang disampaikan oleh seorang sastrawan Indonesia, Ranang Aji SP, dalam sebuah artikel berjudul “Sastra Kini di Antara Pilihan Bentuk”.⁴
Pada dasarnya, seperti yang dikutip Ranang Aji SP, dalam karya sastra posmodernis sering menggunakan teknik pastiche, di mana orisinalitas karya sastra tetap ada, meski mengadopsi imajinasi pengarang sebelumnya. Teknik ini menjadi ciri khas sastra posmodernis. Yang mana, orisinalitas ini didukung oleh hipotek (kebendaan) dan homage (penghormatan) kepada karya sebelumnya.
Dalam perkembangannya, karya sastra selalu menjadi polemik yang tidak berkesudahan, terutama dalam menelisik karya-karya sastra yang diduga dilakukan sebagai karya plagiat. Bahkan sampai ditemukannya kecerdasan buatan (AI), buah dampak dari kemajuan teknologi, istilah plagiat menjadi fenomena yang selalu ramai dibicarakan. Pada titik ini, apakah ruang atau dimensi metafisika mampu menyitir imajinasi manusia yang memengaruhi objektivitas sebuah karya?
Persoalan yang kerap kali bersinggungan dengan pendapat-pendapat di ruang publik, salah satunya tentang bagaimana cara mendefinisikan sebuah karya yang dihasilkan atas imajinasi orang lain. Apakah bentuk karya sastra demikian bisa dianggap sebagai plagiasi? Sebetulnya hal semacam ini sudah ada sejak lama. Atau, apakah karya demikian masih terjaga orisinal dan objektifitasnya? Dalam prinsip karya sastra posmodernis ini dibenarkan, seperti yang disebutkan di atas, adanya intertekstualitas pada teknik pastiche.
Kritik sastra merupakan bagian terpenting dalam ekosistem sastra, tetapi perlu diingat jangan sampai kebebasan berekspresi dan berkreasi terbelenggu oleh kritik yang bersifat menghakimi atau penindasan terhadap pemikiran sastra. Karena seyogianya perkembangan sastra itu adalah sebuah fase dari pembacaan karya-karya sastra sebelumnya, menuju sastra modernis hingga posmodernis.
Ada baiknya kita menelusuri peradaban sastra dari catatan-catatan sejarah sastra. Ketika pemikiran Romawi dan Yunani dalam bentuk naskah-naskah kuno kembali ditemukan, saat itu terlihatlah betapa pentingnya membaca sastra, sejarah dan filsafat. Mengapa? Karena di dalam sastra, orang diajak bertemu dengan kisah manusia, penderitaannya, hidup dan mati, serta pilihan-pilihan yang tidak selalu tegas. Dan sastra mengajarkan orang berbicara dengan fasih, melatih seni bicara dan seni berbahasa. Yang kemudian menggerakkan pemikiran, sehingga orang dapat mengemukakan ide-idenya dengan tepat.
Sastra bukan sekadar rangkaian kata-kata dalam buku; ia cermin peradaban yang merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan, sejarah dan emosi terdalam manusia. Sastra telah mengubah sudut pandang kita dalam membentuk cara untuk memahami kehidupan, memengaruhi pemikiran, bahkan menginspirasi perubahan sosial. Tetapi kenapa dalam kehidupan sastra, muncul sikap pesimistis yang mementahkan pemikiran-pemikiran bersih? Apakah karena bayang-bayang kemiskinan selalu menghantui kehidupan pesastra!?
Jika kemudian kita melihat apa yang terjadi pada sastra Indonesia kini, ada keprihatinan yang perlu diwaspadai. Sastra mulai kehilangan bahasa kemanusiaan dan bahasa cinta, meski kita tidak menampik kehadiran karakter-karakter modernis yang kuat. Tetapi ini masih sangat minim. Ditambah persoalan dasar secara umum, pasar pembaca yang kian sepi. Dan kondisi keprihatinan yang terus-menerus menjadi kubangan pesimistis, salah satunya muncul pemikiran dari para pengarang untuk mencari jalan pintas, dengan menghindari proses kurasi ketat. Cukup banyak pengarang, terutama kalangan pemula yang berorientasi pada identifikasi sosial.
Dengan alibi pembenaran, bahwa semakin banyak orang yang tertarik dan menggeluti dunia sastra, seolah-olah mengasumsikan literasi sastra menjadi sesuatu yang menggiurkan. Problem ini terkadang tanpa disadari telah memunculkan kesenjangan kualitas karya-karya sastra. Meski di era teknologi digital banyak membantu dalam informasi cepat. Bukan dengan serta-merta, semakin menjamurnya karya-karya sastra yang dihasilkan, akan berbanding lurus dengan iklim sastra yang sehat.
Faktanya, dunia sastra khususnya di Indonesia belum mampu sepenuhnya berkontribusi nyata untuk menumbuhkan semangat dan kematangan karya-karya selevel internasional. Pegiat sastra masih sering terjebak dengan fenomena sosial dan politik, yang memengaruhi perilaku kehidupannya. Stigma pesimistis masih mengiringi kreativitas para pegiat sastra. Karya sastra lebih cenderung pada gaya-gaya metafora, yang sejatinya masih minim bersifat pedagogis.
Seyogianya, iklim sastra yang bagus harus dibangun dengan kesadaran kolektif. Termasuk sastra akademisi juga terlibat. Sekat yang membatasi ini seharusnya menjadi cara pandang bersama, antara para praktisi sastra, baik sastrawan berlatar belakang akademisi maupun sastrawan otodidak. Jadi, sastra itu seharusnya memberi nilai bagi kelangsungan pendidikan. Sastra harus ditumbuhkan dengan prinsip-prinsip keilmuan, karena menyangkut etika dan estetika.
Dalam persinggungan sudut pandang, tentu kritik itu tidak semata-mata dalam konteks sastra. Karena bagaimanapun juga, sastra masih sangat bergantung kepada dunia pendidikan. Kenapa demikian? Karena ruang pendidikan formal secara sistematis diatur oleh kebijakan dan hukum positif. Pada umumnya, gerakan-gerakan sastra, baik secara individu maupun kelompok, sering tidak didukung oleh syarat legalitas formal.
Ini tentu bukanlah sebuah premis, jika pengajar terbaik adalah mereka yang mampu mengajarkan dan menunjukkan keburukan serta kegagalan sebuah bangsa sambil tetap mengajarkan cara mencintainya. Di titik ini, kritik kaum terdidik tidak boleh dipenggal, karena seberapa pun pahitnya, ia sepadan dengan tujuan-tujuan nasional suatu bangsa. Untuk mencapai ini, tentu dibutuhkan iklim yang sehat, dan yang beretika. Sementara dari pegiat sastra individu, sebuah kritik bagai pelampiasan rasa ketidakpuasan pribadi; bisa jadi dendam terselubung atas nama karya sastra.
Pada saat yang sama, meski kerja edukasional adalah kerja individual, nasib kemerdekaan berinovasi dalam meningkatkan mutu karya sastra harus diperjuangkan secara kolektif. Seperti sastrawan, seyogianya mulai mengorganisasi yang berbasis profesi untuk mempertahankan dan memperluas kemerdekaan kesastraan secara umum.
Di sini, kita sering terjebak pada persinggungan yang krusial antara kebebasan berpikir dan identitas pengarang/sastrawan. Identitas pribadi tidak ditumbuhkan melalui doktrin; disiplin; dan gelora propaganda, melainkan dengan pembentukan karakter dan perilaku simultan antara sesama sastrawan. Ada kalanya sebuah karya harus dibangun dengan impian besar, dengan imajinasi besar, tetapi tentunya tidak sekadar itu. Setiap pengarang untuk menghasilkan karya-karya bagus, sudah semestinya juga banyak belajar termasuk membiasakan diri dengan budaya membaca.
Skeptisisme sastra hingga memunculkan karya-karya bermutu rendah (inferior), karena kegagalan ini tidak disadari sedini mungkin oleh pengarang. Persoalan layak atau tidak layak bagi karya sastra yang dimuat untuk konsumsi publik, sering kali menambah daftar panjang karya sastra bermutu rendah. Pada titik ini, ada beberapa kasus per kasus yang menjadi penyebab. Ini memang sangat pragmatis, mengingat karya sastra bersifat imajiner dan subjektif.
Sastra sering dianggap sesuatu yang abstrak, dan kurang berdampak positif bagi eksistensi kehidupan. Meski acapkali sastra memunculkan ide-ide brilian. Histori peradaban yang juga terlahir dari sebagian besar teks-teks sastra dianggap tidak ada relevansinya dengan kondisi kekinian, yang justru dalam polemik pemikiran global, sastra di era kini sudah mulai kehilangan bahasa kemanusiaan dan bahasa cinta, yang menjadi tonggak peradaban.
Menyitir tentang subjektivitas sastra, Ranang Aji SP pernah menawarkan gagasan melalui tulisan esai: “Bukan Sastra Inferior” (Kompas, 24 April 2022). Di mana gagasan sastra konstektual lahir akibat para sastrawan terlalu berkiblat pada standar universal (Barat). Ini dikatakan sebagai embrio yang pantas dirawat untuk menghasilkan bentuk sastra Indonesia yang tidak inferior.
Gagasan yang dimaksud di sini, adalah melawan apa yang disebut “keuniversalan” sebagai konsep dari sastra konstektual. Faktanya, tidak ada ukuran yang sama atau universal dalam hal apa pun, semua terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Sebuah kegagalan bagi praktisi sastra, akhirnya sastra dianalogikan dengan mencari cara dan jalannya masing-masing.(*)
Referensi:
¹) Sous les Tilleuls (Bahasa Perancis) yang diartikan secara harfiah adalah di bawah pohon linden, merupakan karya sastra Jean-Baptiste Alphonse Karr yang diterbitkan pada tahun 1832 (Goodreads);
²) Preludes for Memnon diterbitkan pada tahun 1931. Buku ini ditulis oleh penyair dan kritikus Amerika, Conrad Aiken. Kumpulan puisi yang berisi tema-tema tentang waktu, kematian, dan kesadaran diri;
³) Diterjemahkan secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia: Prajurit Muda yang Mati Tak Berbicara (Sumber: National Park Service.gov);
⁴) Artikel ini diterbitkan Harian Kedaulatan Rakyat pada tanggal 20 Agustus 2021.
--------------------------
VITO PRASETYO
Sastrawan dan peminat pendidikan.