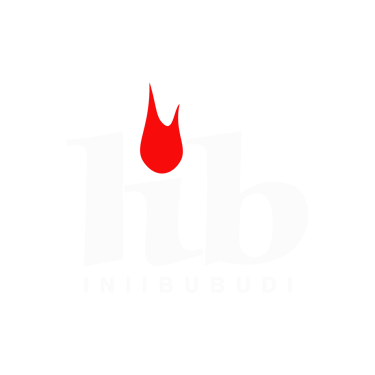Adikku, Mala
CERPEN
Karya: Daisy Rahmi
9/1/2025


POHON-POHON yang tegak di pinggir jalan seperti berlari kala mobil melaju. Di dalam mobil aku duduk bergeming. Yang terjadi sangat mendadak, semua terasa seperti sebuah mimpi buruk. Kukerjapkan pelupuk mata melawan rasa panas yang menusuk. Aku tak boleh menangis karena Mala pasti bingung.
“Abang,” ujar Mala sambil menatapku. Baru kini kusadari matanya mirip mata Ibu. “Kita mau ke mana?”
Aku merengkuhnya. Sekarang hanya dialah milikku. Paman yang duduk di samping sopir taksi menyaksikan adegan di kursi belakang melalui kaca spion. Pria tersebut menjawab ramah.
“Kalian berdua akan tinggal di rumah Paman, Mala. Kau senang, kan?”
“Oh, iya,” gumam Mala tak yakin sebelum bermain lagi dengan bonekanya.
Setelah terhenti karena lampu merah, mobil kembali bergerak. Meninggalkan tempat-tempat yang kukenal, meninggalkan kota kelahiranku.
Sejam berselang kendaraan itu sampai di tujuan. Paman membayar ongkos taksi dan menyuruh kami mengikutinya. Aku meraih koper lalu keluar sambil mengenggam tangan Mala. Gadis cilik itu belum mengerti apa yang terjadi. Usia empat tahun masih terlalu kecil untuk memahami kematian. Butuh beberapa tahun lagi sebelum adikku paham bahwa kami telah yatim piatu.
Baru kali ini aku ke rumah Paman. Rumah yang tidak besar itu terlihat asri dengan pot-pot tanaman hias di balik pagar. Batu-batuan tersusun rapi membentuk jalur jalan menuju teras yang berubin putih. Tiga bocah lelaki sedang bermain di sana.
Paman tersenyum pada kami.
“Ayo masuk,” ajaknya.
Mendengar pagar dibuka, salah seorang dari anak itu berpaling. Senyumnya mengembang melihat sosok yang datang.
“Ayah pulang!” teriaknya girang lalu lari menghambur diikuti saudara-saudaranya.
Tiga anak tersebut mengerumuni kami, begitu senang ayahnya pulang. Mala merapatkan tubuhnya padaku. Paman merangkul putra-putranya, membimbing ketiganya ke teras. Aku dan Mala mengikuti dari belakang.
“Ini sepupu kalian, Al dan Mala,” Paman memperkenalkan kami. “Mereka akan tinggal bersama kita.”
Aku menyambut uluran tangan tiga bersaudara itu. Mala mencontoh dengan malu-malu. Paman menyuruh kami semua masuk rumah usai perkenalan singkat. Diantarnya diriku dan Mala ke kamar yang akan kami tempati.
“Ini kamar kalian,” ujarnya sambil membuka pintu.
Ruangan itu hanya berisi satu tempat tidur dan satu lemari. Cat dindingnya sedikit kusam.
“Kau terpaksa tidur di lantai, Al.”
“Tak apa, Paman.”
“Bereskan barang-barang kalian. Sebentar lagi makan malam.”
Aku mengangguk.
Paman meninggalkan kami sambil menutup pintu di belakangnya. Mala merebahkan tubuh ke kasur. Dipandangnya aku penuh tanya.
“Abang, mana Ibu? Aku ingin bertemu Ibu.”
“Mala, bantu Abang menaruh baju-baju ini ke lemari,” ucapku mengalihkan perhatiannya.
Anak itu menurut. Aku buka koper kemudian bersama adikku memindahkan pakaian-pakaian yang tersusun di dalam ke lemari.
Mala langsung tidur pulas setelah makan malam. Kebalikan dengan diriku. Punggung sakit beradu dengan kerasnya lantai, meski telah kualasi dengan selimut tebal. Potongan-potongan gambar berkelebat di depan mata. Pemakaman, liang lahat, Paman yang berdiri mendampingiku, serta rasa getir menyadari tanggung jawab membesarkan Mala kini jatuh ke pundakku.
Samar terdengar suara orang bicara. Aku bangkit, mengintip melalui celah pintu yang kubuka dengan hati-hati. Paman dan Bibi ada di luar. Bibi terlihat kesal.
“Kenapa kau bawa mereka ke sini?” Aku dengar omelan Bibi. “Kan ada kerabat lain yang bisa menampung.”
“Jangan keras-keras,” cegah Paman lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. “Aku adik ibu mereka. Keluarga terdekat.”
“Tapi kenapa harus keduanya?”
“Aku tidak tega memisahkan mereka.”
“Kita bukan orang kaya. Anak kita sendiri tiga orang. Bagaimana cara menyediakan biaya hidup dan pendidikan untuk dua anak lagi?”
“Pasti ada jalan. Tenanglah. Ayo tidur.”
Suami istri itu pergi. Pintu kamar kututup kembali, berbaring di lantai dan berusaha tidur.
Mala mulai nyaman tinggal di rumah Paman. Anak itu cepat akrab dengan saudara-saudara sepupunya dan sering bermain bersama. Suatu hari Paman mengajakku ke bengkel miliknya. Hari-hari berikutnya aku selalu pergi ke sana untuk membantu sambil belajar tentang seluk beluk perbengkelan. Percakapan yang tak sengaja kudengar membulatkan tekad untuk mandiri.
***
Usia 23 tahun aku kembali ke kota kelahiran. Dengan bantuan modal dari Paman dan tabungan hasil kerja sebelumnya, kubuka bengkel di tepi jalan raya. Mala yang saat itu berumur 11 tahun kutitipkan di rumah Paman. Perlahan usaha yang kurintis mulai menghasilkan laba. Kucicil utangku pada Paman dan membawa Mala tinggal bersama.
Aku makin giat bekerja sejak serumah dengan Mala. Tidak pernah terlintas keinginan mencari calon pendamping hidup. Mala membayar kerja kerasku dengan nilai-nilainya. Adikku tumbuh jadi gadis cemerlang dan selalu berprestasi. Kehidupan kami berjalan tanpa gejolak berarti sampai adikku berusia 17 tahun. Aku terlalu terfokus pada pendidikan Mala hingga melupakan pergaulannya.
Sore itu seorang remaja mengantar Mala pulang. Dia pergi sebelum aku sempat bertanya. Mala membisu. Ia mengurung diri di kamar. Esok harinya, sepulang dari bengkel, kudapati gadis itu tergeletak tak sadarkan diri di kamar mandi. Darah menggenang di lantai, di antara kakinya. Adik perempuanku meninggal di rumah sakit karena pendarahan setelah minum obat penggugur kandungan.
Mala dimakamkan di dekat Ayah dan Ibu. Aku tak beranjak pergi meski keadaan sekitar telah sepi. Mata tertuju ke gundukan tanah merah, menyesali diri karena lalai mengawasi.
“Ini bukan salahmu, Al,” kata Paman seakan tahu yang kupikirkan. Beliau berdiri di sampingku, seperti belasan tahun lalu.
“Yang kau lakukan selama ini luar biasa, mengambil alih tugas orangtuamu.”
Paman menepuk bahuku sambil tersenyum penuh simpati.
“Kau sudah memberi yang terbaik untuk Mala. Berhentilah menyalahkan diri sendiri.”
Keesokan hari dua orang bertamu ke rumah. Seorang wanita dan remaja lelaki yang aku kenali sebagai orang yang mengantar Mala pulang. Kupersilakan mereka masuk. Setelah kami duduk berhadapan, si wanita menjelaskan maksud kedatangannya.
“Saya minta maaf karena baru sekarang berkunjung,” ucapnya sedikit tersendat, “Saya memahami perasaan Anda. Tahun lalu anak bungsu saya meninggal. Saya mengerti yang Anda rasakan.”
“Tapi,” Digenggamnya tangan si anak yang tertunduk. “Putra saya masih sangat muda. Dia sangat menyesal dengan semua yang terjadi, jadi saya mohon Anda tidak memperpanjang masalah ini.”
Kutatap remaja yang menghamili Mala. Wajah pucat yang sebagian tertutup rambut, jari-jari tangan gemetar di pangkuan. Adikku sama bersalahnya dengan dia. Apa pun kesalahan bocah ini, sangat tak adil bila ia harus menanggungnya sendirian. Mataku beralih pada ibu yang resah.
“Saya tidak akan melaporkannya pada polisi kalau itu yang Anda cemaskan.”
“Oh … Terima kasih ….”
Ekspresi lega menghapus kegelisahan di wajahnya. Wanita tersebut membuka tas, meraih sesuatu dan meletakkannya ke meja.
“Saya tahu ini tak mungkin menghilangkan kesedihan Anda, tapi tolong terimalah sebagai permintaan maaf.”
Aku membisu, menatap amplop putih di meja. Kemarahan bergolak. Muak pada golongan yang menganggap semua bisa diselesaikan dengan uang.
“Ambil kembali dan silakan keluar dari sini,” kataku dingin.
Wanita di hadapanku tergagap. Tangannya meraih amplop kemudian memasukkan ke tas. Wajahnya merah padam.
“Maaf … maaf ….” ucapnya terbata.
Wanita tersebut menarik si anak berdiri.
“Cepat minta maaf.”
Remaja tersebut melakukan perintah sang ibu. Detik berikutnya keduanya pergi.
***
Empat bulan kemudian ….
“Jadi keputusanmu sudah bulat?”
“Ya, Paman. Sebuah perusahaan di Sulawesi Utara membuka lowongan pekerjaan. Saya melamar dan diterima.”
“Kenapa jauh sekali?” tanya Bibi yang baru datang. Tangannya membawa nampan berisi segelas minuman. Usai menaruh gelas di depanku, wanita itu duduk di sebelah suaminya.
Aku tersenyum.
“Sekalian cari pengalaman, Bibi.”
“Kapan berangkat?”
“Bulan depan.”
“Bagaimana dengan bengkelmu?” tanya Paman.
“Teman saya sudah setuju untuk membelinya.”
Ini keputusan mendadak tapi yang terbaik. Aku harus menemukan lagi tujuan hidup setelah Mala tiada.
Pasangan suami istri itu mengantarku ke pelabuhan di hari keberangkatan. Portir lalu lalang, sibuk mengangkut barang-barang penumpang ke kapal. Terdengar riuh rendah seruan pedagang menawarkan jualan. Sekelompok orang berteduh di bayangan gedung, menghindari sengatan matahari. Kulirik jam di pergelangan tangan. Sudah waktunya.
“Saya berangkat, Paman, Bibi. Salam untuk adik-adik.”
Paman menyalamiku.
“Jaga dirimu di sana.”
“Baik, Paman.”
Bibi tersenyum.
“Sering-seringlah berkabar.”
“Baik, Bibi.”
Kapal laut berangkat diiringi lambaian tangan para pengantar. Lunasnya mengiris air, membawaku meninggalkan pulau Jawa.(*)
--------------------------
DAISY RAHMI


Cerpenis kelahiran Manado. Cerpennya dimuat di berbagai media massa. Kini tinggal di Jakarta. Buku kumpulan cerpen (solo)-nya, antara lain: Kepak Sayap Merpati (Alinea Publishing, 2022), Dunia Alika (IWP Media Publishing, 2025). Antologi: Musim Bahagia (Gigih Mandiri Pustaka, 2022), Yang Tak Diketahui (Alinea Publishing, 2022), Kembalinya Imam Surau (Phoinex Publisher, 2022).