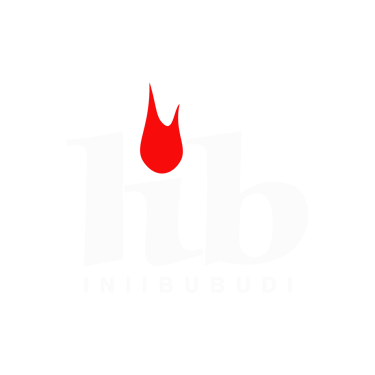Film "Gowok": Momen Musik Kristal dan Bagian yang (Kurang) Masuk Akal
ESAI
Oleh: Akhmad Idris
9/1/2025


KEHADIRAN GOWOK dalam deretan film nusantara memang terasa sebagai angin segar—sebagai pengetahuan maupun upaya kesetaraan. Sebagai pengetahuan, film Gowok memerluas kategori pekerja dalam ranah seksualitas: ada yang diperlakukan sebagai ‘guru’ dan ada juga yang diperlakukan sebagai ‘buruh’. Di sisi lain, sebagai upaya kesetaraan, film Gowok tampak jelas ingin menunjukkan upaya-upaya perempuan dalam menentukan dan mewujudkan mimpi. Kendati seperti itu, ada aspek lain yang membuat saya tertarik untuk membuat tulisan ini, yakni momen-momen musikal yang saya sebut ‘musik kristal’ di sepanjang film. Tak luput juga tentang satu gagasan penting di dalam film yang menurut hemat saya mengalami ‘gagal rumus’. Kemudian bagian terakhir adalah tentang penggunaan kata gowok dan ‘turunannya’ yang tampak rancu.
Ketika Musik Menghentikan Waktu
Musik di dalam film kerap dianggap tidak sepenting alur cerita dan akting tokoh-tokoh di dalamnya. Oleh sebab itu, tak jarang saya menemui orang-orang yang tidak memedulikan momen-momen musikal di dalam film. Alasannya sederhana, kita nonton film ya untuk melihat ceritanya, bukan mendengar musiknya, kata seorang teman. Padahal dalam beberapa momen tertentu, musik bisa menjadi pemicu emosional yang lebih mudah diingat daripada isi cerita film itu sendiri. Saya pernah membuktikannya sendiri saat melihat sebuah cuplikan film di Youtube, tiba-tiba teman saya bertanya Itu film apa? Saya menanggapinya dengan umpan balik, coba kamu tebak. Teman saya terdiam cukup lama, hingga muncul sebuah lagu yang menjadi soundtrack-nya. Tiba-tiba dia langsung bisa menjawab dengan tepat judul filmnya—karena sama persis dengan judul lagunya, yakni Laskar Pelangi.
Lebih dari itu, momen-momen musikal di dalam film tidak sekadar menambah keindahan, tetapi juga upaya penyampaian pesan. Tak berlebihan jika Phil Powrie (2023) dalam The Acoustic Wound: Reflections on the Crystal-Song in Five American Films menggunalkan istilah ‘Lagu Kristal’ untuk menyebut lagu-lagu yang seolah mampu menghentikan waktu di dalam film. Sementara di dalam film Gowok, saya menyebutnya dengan istilah ‘Musik Kristal’, karena momen-momen yang seolah mengkristal tersebut terjadi tanpa disertai lagu—hanya musik, namun waktu seolah berhenti dalam momen yang seharusnya singkat namun menjerat. Momen-momen itu di antaranya saat Ratri mendapatkan ‘serangan balik’ dari Kamanjaya atas pernyataan menjadi gowok penerus Nyai Santi, saat Kamanjaya dan Nyai Santi melakukan asmaragama, saat Ratri membaca surat-surat dari Kamanjaya yang disembunyikan oleh Nyai Santi, dan saat Ratri menangisi Kamanjaya yang sudah mati.
Waktu tak lagi bergerak linear, tiba-tiba melambat, menciptakan sisi afektif yang berbeda-beda saat musik mulai beralun. Mulai dari pengkristalan rasa gelisah, gairah, hingga nostalgia. Pengkristalan rasa gelisah dapat dinikmati ketika Ratri dengan semangat bercerita kepada Kamanjaya tentang syarat-syarat menjadi Gowok di atas batu-batu sungai sembari mencuci baju. Satu di antara syaratnya adalah menjadi gowok berarti melajang seumur hidup. Tiba-tiba Kamanjaya bertanya balik, berarti kamu tidak menikah? Tiba-tiba percakapan terhenti begitu saja. Menyisakan suara deras air sungai, gerakan tangan Ratri mengucek pakaian, anggukan Ratri tanpa suara, tatapan kosong mata Ratri, dan musik sendu yang terus mengiringi hingga berganti scene. Keheningan ini justru memantik riuh pertanyaan tanpa jawaban: benarkah Ratri memang ingin menjadi gowok? Apakah Ratri melakukannya karena terpaksa, tak berdaya, hanya bisa pasrah? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya….
Momen ‘musik kristal’ selanjutnya adalah adegan 17+ dalam ritus asmaragama sebagai bagian utama dari proses menggowok. Bagian ini tentu saja menjadi adegan ikonik dari film Gowok, saat Kamanjaya digowok oleh Nyai Santi—namun yang ada di bayangan Kamanjaya adalah potongan-potongan kejadian saat Kamanjaya bermesraan dengan Ratri. Potongan-potongan kejadian ditampilkan seperti pemutaran memori ulang dengan latar musik bernada sendu-romantis. Musik ini membawa penonton ke dalam keindahan ingatan masa lalu sekaligus bayangan cerah masa depan. Setiap potong kejadian disesuaikan dengan empat tahapan asmaragama yang dimulai dari asmaratura dan diakhiri dengan asmaragama.
Tak hanya mengkristalkan momen, musik juga bisa memutarbalikkan suasana—dari amarah beralih ke rasa rindu yang membuncah. Momen ini dapat disaksikan saat Ratri menemukan surat-surat dari Kamanjaya yang disembunyikan oleh Nyai Santi. Musik yang awalnya tegang karena amarah Ratri atas perbuatan Nyai Santi secara ‘mulus’ berganti menjadi musik sendu sebagaimana momen-momen sebelumnya saat Ratri masih bermesraan dengan Kamanjaya (dulu). Dalam momen musikal ini, amarah Ratri seolah mendadak lenyap, berganti dengan rasa sesal yang kian sesak. Setelah semua surat telah terbaca, musik mendadak ‘balik kucing’ ke nada tegang. Amarah Ratri kembali terasa, siap melancarkan berbagai pertanyaan hingga hardikan kepada Nyai Santi. Dalam momen ini, musik adalah pengatur fluktuasi emosi yang terkadang tidak disadari oleh penikmatnya.
Mantra Atmaprawesa: Kegagalan dalam Membuat ‘Rumus’
Secara garis besar, cerita dalam film Gowok tercipta gegara keampuhan mantra dalam Serat Atmaprawesa. Mantra ini mampu mengikat pasangan dalam kesucian cinta—sehidup-semati. Memang terlihat istimewa, namun menjadi bencana bagi orang-orang yang tidak setia. Dari mantra inilah konflik bermula. Ratri pada dasarnya adalah anak haram dari hubungan gelap antara Lono dan Jenar, padahal Lono telah mengikat janji cinta sehidup-semati dengan istrinya yang bernama Ningrum. Janji setia yang diikrarkan oleh Lono menggunakan mantra atmaprawesa yang ia minta kepada Nyai Santi. Pada awalnya memang mantra tersebut seolah menguatkan cinta Lono dan Ningrum, namun semua menjadi musibah saat Lono tergoda dengan perempuan lain yang bernama Jenar. Terjadilah perselingkuhan hingga lahir seorang bayi mungil yang bernama Ratri. Dari sinilah tragedi berdarah dimulai, Ningrum sakit hati dan menghabisi nyawa Ningrum sekaligus Lono—dan diri Ningrum sendiri, menyisakan bayi yang bernama Ratri.
Dari tragedi berdarah tersebut, ‘rumus’ dari mantra Atmaprawesa dijelaskan oleh Nyai Santi kepada Ratri. Nyai Santi mengatakan bahwa meskipun mantra Atmaprawesa menjadi lambang kesetiaan pasangan, mantra itu juga bisa menjadi malapetaka bagi orang yang berikrar jika ia mengingkari kesetiaannya. Mantra itu akan membunuhnya beserta pasangannya. Kurang lebih seperti inilah ‘rumus’ dari mantra Atmaprawesa. Sialnya lagi, mantra ini justru kembali menemui takdir buruk gara-gara diikrarkan oleh Ratri saat menggowok Bagas. Artinya, Ratri telah berikrar janji cinta sehidup-semati dengan Bagas, padahal Ratri melakukannya atas dasar balas dendam terhadap Kamanjaya. Konsekuensinya adalah Ratri tidak boleh tergoda dengan laki-laki lain. Jika Ratri menikah dengan laki-laki lain, maka Ratri (dan Bagas) akan mati. Kurang lebih seperti inilah yang terjadi jika sesuai dengan ‘rumus’ yang telah dikonstruk sejak awal.
Anehnya, saat Bagas mati terbunuh, Ratri tidak (ikut) mati. Malah di akhir cerita, Ratri telah memiliki dua anak—meskipun tidak diperlihatkan sosok suaminya. Bukankah berarti Ratri telah melanggar ikrarnya sendiri untuk sehidup-semati dengan Bagas? Jika Ratri pada akhirnya tetap baik-baik saja, apakah ini berarti ada kegagalan ‘rumus’ dalam film ini? Ataukah mantra Atmaprawesa itu hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan perempuan adalah pengecualian? Apakah ini berarti sebuah ikrar sumpah hanya layak diucapkan oleh laki-laki, sedang ikrar perempuan dianggap ‘sepele’ saja? Banyak sekali pertanyaan yang akan terus bergulir gegara kegagalan ‘rumus’ Atmaprawesa ini—yang pada ujungnya tetaplah menjadi tanda tanya.
Pemaknaan yang Rancu atas Gowok
Ada yang aneh dalam penciptaan bentuk turunan dari kata dasar “gowok”. Dari kata dasar gowok, muncul beberapa bentuk turunan seperti gowokan; menggowok; dan digowok. Memangnya apa yang aneh? Di bagian pembuka film ditampilkan sebuah pemaknaan istilah tentang term “gowok”, yakni seorang wanita yang disewa untuk mengajarkan seksualitas kepada laki-laki remaja (yang sudah berkhitan) atau yang hendak menikah—kurang lebih seperti ini. Sederhananya, term “gowok” dimaknai dan dikategorikan sebagai nomina atau kata benda yang sekaligus menjadi kata dasar. Dengan bekal dasar inilah saya mengikuti alur cerita dan sajian visual film Gowok. Beberapa menit setelahnya, ditampilkan sebuah rumah berarsitektur cina yang di bagian gerbang masuknya tergantung sebuah papan nama yang berbunyi gowokan.
Secara morfologis, kata gowokan merupakan bentuk turunan dari gowok yang mendapatkan sufiks –an. Bagian inilah yang membuat saya bingung, karena kemungkinan dua makna yang dihadirkan. Makna yang pertama diperoleh berdasarkan sajian visual, sedangkan makna yang kedua diambil berdasarkan telisik referensial. Jika melihat tampilan visual film (papan nama di gerbang masuk), gowokan seolah dimaknai sebagai tempat. Berbeda dengan pemaknaan yang kedua, gowokan dimaknai sebagai tradisi berdasarkan kajian ilmiah yang dilakukan oleh Dyah Siti Septiningsih (2010) dalam Gowokan, Persiapan Pernikahan Laki-Laki Banyumas. Lalu, pemaknaan manakah yang dipakai?
Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya sederhana, yakni author is dead—pembaca atau penonton yang menentukan maknanya. Terlepas gowokan sebagai tempat atau tradisi, proses pembentukan kata gowokan terasa aneh. Bambang Yulianto (2011), guru besar Universitas Negeri Surabaya dalam Penuntun Praktis Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar menyatakan bahwa sufiks –an tidak diperlukan pada proses pembentukan kata yang berasal dari kata benda. Logika sederhananya seperti ini, sufiks –an berfungsi sebagai pembentuk nomina, lalu untuk apa menominakan kata yang memang sudah nomina? Seperti contoh sekolahan yang sudah cukup dengan kata sekolah dan ruangan yang sudah cukup dengan kata ruang. Implementasinya, bukankah gowokan juga sudah cukup dengan kata gowok? Atau justru maksud dari gowokan adalah tempat untuk melakukan gowok? Apa memang kata gowok terasa lebih pas jika dijadikan sebagai verba daripada nomina?
Puncak kegelisahan saya tiba dalam dialog-dialog selanjutnya yang mengandung dua bentuk turunan selanjutnya (setelah gowokan), yakni menggowok dan digowok. Di dalam film Gowok, kata “menggowok” bermakna gowok mengajari laki-laki tentang seksualitas dan “digowok” berarti laki-laki diajari oleh gowok tentang seksualitas. Dialog utuhnya kurang lebih seperti ini, aku akan mulai menggowoknya dan cucuku akan digowok di sini. Secara morfologis, kata di bisa dikategorikan menjadi dua bentuk, yakni kata depan dan prefiks. Oleh sebab itu, di dalam kata digowok sudah pasti termasuk awalan atau prefiks. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, prefiks di- bermakna dikenai suatu tindakan. Misalnya kata dipukul yang berarti dikenai pukul. Atas dasar inilah kata digowok dapat dimaknai dikenai gowok. Jika memang seperti itu, bukankah gowok memang lebih pas dimaknai sebagai suatu tindakan alias kata kerja?
Begitu juga kata menggowok yang dibentuk dari kata dasar gowok yang diberi awalan meng-. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, meng- dikategorikan sebagai prefiks pembentuk verba yang memiliki beragam makna, mulai dari menjadi; menyerupai; makan/minum; menuju; mencari; mengeluarkan bunyi; menimbulkan kesan seperti; menghasilkan; menyatakan; hingga dasar verba. Berdasarkan penggunaan kata menggowok di dalam film, prefiks meng- di sini termasuk kategori dasar verba karena berarti melakukan suatu tindakan. Jika hendak dicoba satu per satu, maka hasilnya akan seperti ini: menggowok tidak mungkin bermakna menjadi gowok, menyerupai gowok, makan/minum gowok, menuju gowok, mencari gowok, mengeluarkan bunyi gowok, menimbulkan kesan seperti gowok, menghasilkan gowok, dan menyatakan gowok. Artinya, kata gowok memang pada dasarnya lebih pas dikategorikan sebagai verba daripada nomina.
Menurut hemat saya, gowok (verba) lebih pas dimaknai sebagai mengajari laki-laki remaja tentang seksualitas, sedangkan wanita atau pengajarnya disebuat dengan penggowok (nomina). Kendati seperti itu, bahasa bukan milik pemerhati atau kritikus bahasa. Bahasa adalah milik penuturnya dan bahasa akan dikembalikan (lagi) kepada penuturnya—lebih suka yang mana.(*)
--------------------------
AKHMAD IDRIS
Seorang dosen bahasa dan sastra Indonesia yang sangat tertarik dengan dunia sastra beserta segala tetek bengeknya. Saat ini hampir menyelesaikan studi doktoral di Universitas Negeri Malang lewat Beasiswa Pendidikan Indonesia. Lahir di Surabaya, 1 Februari 1994. Baru-baru ini (tahun 2025), naskah cerita anaknya lolos dalam sayembara cerita anak berbahasa Jawa Balai Bahasa Jawa Timur, naskahnya masuk dalam 30 besar sayembara kritik film Dewan Kesenian Jakarta 2024. Pada tahun 2023, terpilih menjadi satu di antara delapan belas penulis dalam kegiatan Residensi Literatutur yang diadakan Yayasan Gang Sebelah bekerja sama dengan Kemdikbud. Tahun 2022, naskahnya yang berjudul Candirejo dan Variasi Literasi lolos dalam sayembara kajian literasi terapan berbasis konten lokal yang diadakan oleh Perpusnas RI. Tahun 2022, esainya tentang pertunjukan seni di ICAS-Fest menjadi juara 1 dalam lomba kritik seni yang diadakan oleh Pascasarjana ISBI Bandung. Selain mengajar, kesibukan lainnya adalah menulis di media-media lokal maupun nasional serta di beberapa jurnal nasional maupun internasional.