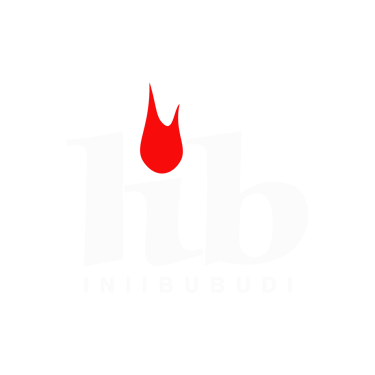Hyang Kretek
ESAI
Oleh: Imam Khanafi
10/3/2025


DI KUDUS, ada sebuah nama yang harum sekaligus menggelegar, meski tak diucapkan dengan doa, ia tetap menempel di dada masyarakatnya: kretek. Bukan sekadar rokok, bukan pula hanya lintingan tembakau bercampur cengkeh. Kretek adalah suara kehidupan. Bunyi “kretek-kretek” dari cengkeh yang terbakar seakan menandai awal suatu peradaban baru di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, kota yang bahkan bukan penghasil tembakau atau cengkeh terbaik, tetapi justru melahirkan sejarah panjang industri ini: Kudus.
Kisahnya bermula dari seorang lelaki bernama Djamhari. Sekitar tahun 1880, ia menderita penyakit asma. Berulang kali sesaknya membuat hidup terasa berat, hingga pada suatu hari ia mencoba mengoleskan minyak cengkeh di dadanya. Ada rasa lega, ada jalan napas yang terbuka. Dari pengalaman sederhana itu, Djamhari lalu berani bereksperimen—tembakau ia campur dengan cengkeh, dibungkus daun jagung, lalu dibakar. Saat itu, terdengar suara khas “kretek-kretek”. Siapa sangka, bunyi kecil dari bara itu akan menggaung ratusan tahun kemudian sebagai identitas bangsa.
Awalnya, lintingan itu hanyalah obat tradisional. Orang menyebutnya rokok obat. Namun, ketika Djamhari mulai memproduksi dan memasarkan, kretek menjelma menjadi bagian hidup masyarakat Kudus, lalu menyebar ke penjuru tanah air. Dari sebuah percobaan pribadi, lahirlah sesuatu yang kemudian menjadi industri raksasa, simbol ekonomi, sekaligus bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia.
Djamhari bukan sekadar cerita turun-temurun. Sejarawan Edy Supratno berhasil menemukan makamnya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari sana ia menyusun jejak historis, bertemu dengan keturunan Djamhari, lalu menuliskannya dalam buku “Djamhari Penemu Kretek: 100 Tahun Sejarah yang Terpendam dan Lika-liku Pencarian Jejaknya.” Penemuan itu menguatkan posisi Djamhari sebagai sosok nyata, bukan mitos.
Nama Djamhari juga telah disebut dalam berbagai karya historis, mulai dari Van Der Reijden (1934), Parada Harahap (1952), hingga Lance Castles (1982). Semua itu menjadi bukti bahwa ia adalah peracik pertama kretek. Tradisi, literatur, hingga penelitian modern bertemu di satu titik: Djamhari adalah penemu yang sesungguhnya.
Sejarah tidak berhenti pada Djamhari. Dari Kudus pula lahir seorang tokoh besar lain: Nitisemito, yang kemudian dikenal sebagai Raja Kretek. Nama aslinya adalah Rusdi, seorang pemuda Kudus yang memulai hidup dari nol. Ia mencoba banyak pekerjaan sebelum akhirnya terjun ke dunia kretek dengan merek Tjap Bal Tiga atau Cap Tiga Bal.
Jika Djamhari adalah penemu, maka Nitisemito adalah pengembangnya. Awal abad ke-20, usahanya berkembang pesat. Ia mendirikan pabrik besar di Kudus, mempekerjakan ribuan buruh, dan memproduksi jutaan batang kretek. Di puncak kejayaannya pada 1914 hingga 1930-an, nama Nitisemito bahkan sampai ke telinga Ratu Wilhelmina di Belanda yang menjulukinya “De Kretek Koning”—Sang Raja Kretek.
Namun, kehebatannya bukan hanya pada bisnis. Nitisemito juga mendukung pergerakan nasional Indonesia secara finansial. Sukarno menyebutnya sebagai contoh nyata pengusaha pribumi yang kaya raya sekaligus berani berpihak pada bangsanya. Kini, namanya diabadikan pada sebuah jalan di Kudus, dan kisah hidupnya dipamerkan di Museum Kretek, sebuah monumen budaya sekaligus ruang ingatan kolektif kota ini.
Tanah Kretek, Hyang Kretek
Kudus, kota yang kecil dan sederhana, tidak memiliki kebun tembakau luas atau pohon cengkeh unggul. Namun justru dari tanah inilah lahir kretek, sebuah produk budaya sekaligus ekonomi yang menghidupi jutaan orang di Indonesia. Kretek bukan sekadar barang dagangan, ia telah menjelma menjadi simbol perjuangan, tanda kehidupan, bahkan jati diri.
Karena itu, kretek layak dipandang sebagai “Hyang Kretek”—sesuatu yang diagungkan, dihormati, dan dimuliakan. Ia adalah pusaka yang lahir dari tangan rakyat kecil, tetapi menjelma menjadi kekuatan besar. Dari Djamhari yang melinting untuk obat, hingga Nitisemito yang membangun kerajaan bisnisnya, kretek selalu berakar pada Kudus, lalu menjalar ke seluruh nusantara.
Hari ini, ketika kita menoleh ke belakang, kita tidak sekadar melihat rokok yang terbakar dan mengepul. Kita melihat sejarah, kerja keras, budaya, sekaligus doa yang terucap dari setiap lintingan. Kudus mungkin tidak punya ladang tembakau terluas, bukan pula penghasil cengkeh terbaik. Tetapi Kudus punya sesuatu yang lebih dari itu: roh kretek. Dan dari sinilah kehidupan itu bermula.
Sejarah kretek di Kudus tidak berhenti pada Djamhari dan Nitisemito. Sampai hari ini, roh kretek tetap berdenyut melalui perusahaan-perusahaan besar yang lahir dan bertahan di kota ini. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Djarum, didirikan oleh Oei Wie Gwan pada tahun 1951.
Sebelum masuk ke dunia kretek, Oei Wie Gwan dikenal sebagai pengusaha petasan bermerek “Leo” di Rembang. Namun, setelah pemerintah melarang industri petasan, ia banting setir ke rokok kretek. Ia membeli sebuah pabrik kecil di Kudus yang sudah lama mati, lalu menghidupkannya kembali dengan merek Djarum. Dari situlah perjalanan panjang dimulai.
Meski sempat dilanda kebakaran hebat pada 1963—tahun yang sama dengan wafatnya Oei Wie Gwan—perusahaan ini tidak ikut padam. Dua putranya, Bambang Hartono dan Budi Hartono, pulang dari bangku kuliah untuk mengurus peninggalan ayah mereka. Dengan tekad kuat, mereka bangkit dari reruntuhan: mencari pinjaman bank, menaikkan gaji pekerja, dan menyalakan kembali bara usaha yang hampir padam. Perlahan, Djarum tumbuh menjadi salah satu raksasa kretek Indonesia, sejajar dengan Gudang Garam, Bentoel, dan Sampoerna.
Kini, Djarum tidak hanya dikenal lewat rokok kreteknya yang merambah pasar internasional, tetapi juga melalui diversifikasi usaha ke bidang elektronik (Polytron), tekstil, hingga mebel. Meski demikian, akar terpentingnya tetap berada di Kudus. Ribuan orang masih bekerja di pabrik Djarum, menggantungkan hidup pada industri yang lahir dari percikan sejarah kretek.
Selain Djarum, kota Kudus juga punya dua perusahaan besar lain, Sukun dan Nojorono, yang turut menjaga nyala api tradisi ini. Bersama-sama, mereka menjadi penopang ekonomi lokal, menyerap tenaga kerja, dan menghidupi masyarakat.
Di titik inilah, julukan “Hyang Kretek” menemukan wujudnya: kretek bukan hanya kisah masa lalu, melainkan kehidupan yang masih terus berdenyut hingga hari ini. Dari Djamhari hingga Nitisemito, dari Djarum hingga Sukun dan Nojorono, Kudus berdiri sebagai tanah kretek—tempat di mana bunyi “kretek-kretek” bukan sekadar suara terbakar, melainkan suara kehidupan itu sendiri.
Jejak Sunyi dalam Sejarah Hyang Kretek
Sejarah kretek di Kudus tidak pernah hanya ditopang oleh satu atau dua tokoh besar. Di balik nama-nama yang kerap disebut, ada sosok-sosok lain yang ikut menyalakan bara dan menjaga asap kretek tetap hidup. Salah satunya adalah Atmowidjojo, atau akrab disebut Atmo, pengusaha kretek Tjap Goenoong Kedoe.
Atmo lahir di lingkungan pedagang Kudus Kulon, sebagai anak bungsu dari pasangan Trunodiwongso dan Nyi Rowo. Seperti watak masyarakat Kudus pada umumnya, ia dikenal ulet, sederhana, tetapi tajam dalam membaca peluang. Sehari-hari penampilannya lebih mirip tukang kebun daripada juragan kretek. Sering kali tamu atau calon agen yang datang ke rumahnya terkecoh, tak menyangka orang bersahaja di depannya adalah pemilik pabrik kretek besar.
Atmo memulai usahanya di Desa Langgardalem, tidak jauh dari Menara Kudus, sebelum kemudian pindah ke Dukuh Pringinan, Desa Kerjasan. Posisinya hanya beberapa langkah dari situs Langgar Bubrah. Dari sanalah Tjap Goenoong Kedoe tumbuh hingga dikenal luas sejak 1912.
Ia bukan sekadar pedagang, tetapi seorang pembangun fondasi. Setahap demi setahap Atmo memperluas usahanya dengan membeli rumah-rumah tetangga untuk dijadikan pabrik. Ia juga melahirkan merek baru seperti Krandjang dan Omah, yang memperkuat posisinya di pasar.
Pada 1939, Parada Harahap, wartawan Tjaja Timoer, datang ke Kudus dan menulis tentang keberhasilan Atmo. Ia menyaksikan langsung bagaimana seorang juragan kretek besar bisa tetap hidup sederhana, berpakaian ala rakyat jelata, namun berpengaruh dalam perniagaan.
Atmo wafat pada 1945, meninggalkan sedikitnya tujuh anak dari pernikahannya dengan Warsini. Anak-anak itu tidak semuanya mengikuti jejaknya, tetapi sebagian meneruskan darah dagang yang diwariskan. Yang paling menonjol adalah Haji Mas Ashadie, anak sulungnya, yang kemudian dikenal sebagai pemilik usaha kretek Cap Delima.
Ashadie sudah berlatih sejak muda. Sekitar 1916, ia bahkan membuat kretek bermerek Terong, dengan bimbingan langsung dari sang ayah. Bahan baku, pekerja, hingga jaringan pemasaran banyak terbantu oleh kedudukan Atmo. Inilah cara Atmo mendidik anak-anaknya: bukan lewat sekolah formal, melainkan melalui praktik wirausaha sehari-hari, khas masyarakat Kudus yang membesarkan industri kretek dari rumah-rumah kecil di gang sempit.
Jejak fisik warisan Atmo masih ada hingga kini. Rumah, bekas pabrik, dan musala kecil di sekitar Pringinan masih berdiri, menjadi saksi bisu masa ketika Cap Goenoong Kedoe termasuk dalam The Big Five perusahaan kretek di Kudus era kolonial.
Filsafat Hyang Kretek
Kisah Atmo menambah lapisan dalam pemahaman tentang Hyang Kretek. Kretek bukan hanya tentang Djamhari sang penemu, atau Nitisemito dan Oei Wie Gwan sang pengembang raksasa industri. Kretek juga hidup dari tangan-tangan pengusaha sunyi seperti Atmo dan anak-anaknya, dari keringat buruh-buruh kecil yang melinting dengan sabar, dari keluarga yang menjadikan rokok bukan hanya barang dagangan, tetapi juga sarana penghidupan.
Di Kudus, kretek adalah roh kehidupan. Ia mencetak sejarah ekonomi, tetapi juga mengubah lanskap sosial. Dari kretek, lahir ribuan lapangan kerja, tumbuh tradisi gotong royong, muncul pergerakan sosial, bahkan ikut menyokong perjuangan bangsa. Kretek bukan hanya sebatang rokok yang terbakar, tetapi peradaban kecil yang terus menyala.
Karena itulah kita layak menyebutnya Hyang Kretek—sesuatu yang diagungkan bukan karena mitos, melainkan karena ia memberi kehidupan. Dari generasi ke generasi, dari buruh linting hingga juragan, dari pabrik kecil hingga raksasa industri, semua adalah bagian dari napas panjang Kudus.
Maka, ucapan terima kasih pantas ditujukan kepada semua: para buruh rokok yang dengan jemari telaten menjaga bara tetap hidup, para pengusaha yang berani menanggung risiko, dan seluruh masyarakat Kudus yang menjadikan kretek bukan sekadar komoditas, tetapi bagian dari hidup bersama.
Kretek, dengan segala asapnya, telah mengajarkan satu hal: bahwa kehidupan bisa lahir dari hal sederhana—dari sebatang rokok yang berisik saat terbakar, tetapi justru di situlah kita mendengar denyut kehidupan sebuah kota. Itulah filsafat Hyang Kretek: sebuah kehidupan yang lahir, tumbuh, dan terus bertransformasi di Kudus.(*)
--------------------------
IMAM KHANAFI
Pegiat literasi dan pengamat seni pertunjukan, tinggal di Kudus. [Foto-foto: Ist]