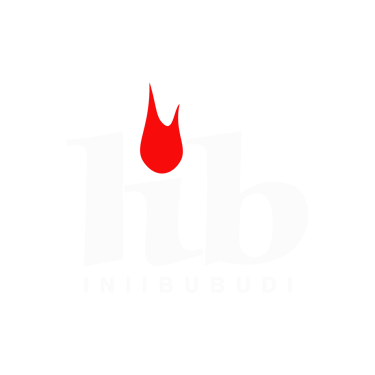Kematian Kedua Nurman Gendung
CERPEN
Karya: Muhammad Lutfi Maula
7/1/2025


DUA minggu lalu, aku mendapat tugas untuk meliput suatu ritus peribadatan warga desa Gugurgunung. Sebuah upacara penyembahan kepada pohon beringin tua yang diyakini warga desa sebagai tempat bersemayam Dewa Anurma, dewa yang dipercaya selalu memberikan kesuburan bagi ladang-ladang warga desa.
Ritual itu dilakukan warga desa Gugurgunung tiap memasuki awal Tahun Naga, lebih tepatnya saat kemarau panjang perlahan mulai menggerayangi sekujur desa. Dan sampai saat ini, sekalipun tak membaca hasil liputanku, aku masih dapat mengingat sekaligus merinci tahap demi tahap peribadatan itu.
Upacara itu dimulai ketika matahari hampir terbenam. Mula-mula, para tetua desa akan merapal mantra-mantra sambil mendongakkan kepala mereka menatap pantulan sinar matahari penghabisan yang tak berselang lama akan lenyap di balik pucuk pohon beringin tua itu. Setelahnya, para ibu serta perempuan-perempuan muda akan menari dan menyenandungkan beberapa bait Kidung Agung dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh warga desa tersebut.
Ketika senandung yang mereka nyanyikan mencapai lirik akhir, di mana seorang sinden yang paling muda di antara mereka mulai menguarkan suara dari tenggorokannya yang terlatih untuk mencapai nada tertinggi yang kemudian meninggalkan gema berkepanjangan, mereka akan membuat sebuah lingkaran mengelilingi sang sinden. Dan pada saat itulah seorang dari kaum bapak atau lelaki-lelaki muda yang terpilih, membawakan tumbal ke tengah lingkaran untuk kemudian meletakkannya di hadapan sang sinden.
Ah, sial. Aku rasa aku tak mampu melanjutkannya. Bagaimanapun, hal itu benar-benar tidak manusiawi dan aku merasa perutku bergejolak tiap mengingat upacara tersebut. Sumpah mati aku ingin sekali melupakan apa yang kulihat waktu itu. Namun pesan singkat dari temanku pagi ini membawa ingatanku kembali.
***
Aku pertama kali bertemu Nurman Gendung di sebuah dangau lapuk di pematang sawah, tengah hari. Sebuah pertemuan tak disengaja sebenarnya. Sebab, hari itu adalah hari terakhirku bertugas di desa Gugurgunung dan aku tak sedang berencana mewawancarai seorang warga pun. Maka pada pagi setelah mengemas barang-barangku, karena bosan hanya bermalas-malasan menunggu jemputan pulang datang di rumah Didin, rumah yang kudiami selama berada di desa Gugurgunung, aku memilih untuk beranjak keluar meski tanpa tujuan pasti.
Semula aku hendak mampir ke rumah Ki Jambroh, salah satu tetua desa, tetapi niat itu kuurungkan karena dalam perjalanan, saat berada tak jauh dari rumahnya aku mendengar geletar bentakan lelaki itu yang ditimpali suara piring-piring atau gelas-gelas pecah dan pekik istrinya. Akhirnya aku terus berjalan hingga tak terasa sampailah aku di tepi sawah.
Di tepian itu, sejauh mataku memandang, tampak seorang lelaki tua bersila seorang diri di sebuah dangau. Dangau itu berjarak selang beberapa meter saja dari bebegig di pematang sawah persis di sebelah aku berdiam. Dan didorong suatu perasaan entah, aku menghampiri lelaki tua itu.
Sesampainya di dangau aku mengucap salam sekenanya. Namun, lelaki tua itu tak menggubris salamku. Ketika kujulurkan tanganku ke hadapannya, barulah ia menyadari kedatanganku ke dangau itu.
“Nurman Gendung. Sebut lengkap namaku seperti orang-orang desa ini memanggilku,” ia mengucapkan ini dalam satu tarikan nafas.
Dari kerut-merut di wajahnya serta perawakannya, lalu rambut, janggut, dan kumis yang sepenuhnya telah memutih, kutaksir umurnya tak berpaut jauh dari Ki Jambroh atau tetua desa lainnya. Bisa jadi lebih muda atau sebaliknya. Aku tidak tahu persis. Yang jelas saat itu aku yakin betul bahwa itu benar-benar pertemuan pertama kami. Selama sepekan berada di desa itu, tak pernah aku bertemu dengannya atau bahkan sepintas menatap wajahnya di berbagai tempat serta acara yang telah kukunjungi. Aku masih ingat betul bagaimana suaranya terdengar seperti tembang-tembang sedih yang pada waktu itu sering kudengar. Ditambah lelaki tua itu memiliki wajah yang begitu durja—sedurja wajah Ibrahim ketika mendapat ilham untuk menyembelih anaknya yang pernah kulihat di buku Kisah-Kisah Nabi semasa bocah, yang menjadikan suaranya kian terdengar parau.
Beberapa jenak kemudian, seraya memandang padi-padi yang mulai bernas, tanpa diminta, lelaki tua yang mengenalkan dirinya sebagai Nurman Gendung itu tiba-tiba berkisah tentang dirinya sendiri:
“Dahulu, ibuku mengandung anak kembar. Bukan kembar raga sebagaimana lazim terjadi, melainkan kembar jiwa. Ya, kau mungkin baru mendengar hal semacam ini pertama kali. Tetapi di desa yang diselimuti keajaiban ini, segala hal muskil dapat terjadi."
“Saat aku lahir, berkat saran tetua desa, ayahku menamaiku Gendung, yang dalam bahasa kami bisa diartikan mirip atau kembar, lalu ibuku melengkapinya dengan Nurman, yang nama itu ia artikan sebagai penerang atau cahaya. Namun tak syak lagi ada kekhawatiran besar yang orang tuaku rasakan kala itu. Sebab adanya campur tangan tetua desa ketika memberikanku nama, tak ubahnya tulah yang menyingkap tabir lebih dini. Dan nahas, keduanya tak mampu mencegah kuasa tersebut."
“Ya, tetua desa akan menjadikan tubuhku yang tak berdaya saat itu sebagai tumbal untuk Dewa Anurma. Mereka datang tepat ketika usiaku memasuki 40 hari. Usai mendengar permintaan tetua desa yang sudah kedua orang tuaku curigai sebelumnya, akhirnya mereka hanya bisa merelakan kepergianku. Pasrah akan keadaan. Sebab ritual mesti terus dilakukan demi kemaslahatan seluruh penduduk desa."
“Maka setelah tiba waktunya, seperti yang kau lihat tempo hari, upacara pun diadakan sedemikian rupa saat itu. Tetapi ada yang berbeda kala itu. Sebab pada momen ketika sinden yang bertugas menggorok leherku menuntaskan tugasnya, sekejap saja sebuah kilatan keajaiban menghampiri tubuhku."
“Di tengah gemuruh pekik ibuku dan rapal mantra dan senandung serta tarian warga desa, aku hidup kembali lalu menangis seperti saat pertama kali keluar dari rahim ibuku. Tangisanku membelah gemuruh upacara tersebut. Semua orang dibuat takjub oleh tangisku, kecuali Ki Buraong."
"Kuberikan ia nama Gendung, karena aku bisa melihat bayi ini memiliki dua jiwa dalam satu raga. Ibunya mengandung bayi yang kembar jiwa, seperti yang pernah terjadi pada buyutku dahulu kala," begitulah terang Ki Buraong. Tak ada yang menimpali, sebab kala itu tuturnya serupa sabda suci. Tentu saja bukan main senangnya kedua orang tuaku terhadap keajaiban tersebut. Dan hal itu yang membuat mereka menyayangiku lebih dari apa pun.
“Lalu, aku hidup seperti anak-anak lelaki pada umumnya yang bisa kau lihat di desa ini. Menghabiskan waktu bermain, bersenda-gurau, dan sesekali mengintip gadis-gadis mandi di sungai. Hingga kemudian, aku beranjak remaja, dewasa, menikah dan memiliki anak, kemudian menua seperti sekarang ini."
“Dan saat inilah, ketika tubuhku mulai meruapkan bau kematian, tak ada yang aku inginkan selain memiliki cucu. Ya, cucu saja tak lebih dan tak kurang. Namun, ketika dunia telah memberikan apa yang kuinginkan, dunia pula yang merampasnya.”
Setelahnya hanya hela nafas. Sesekali desir angin merambah dangau itu, seolah menyapa kami yang terdiam entah berapa lama. Terus terang aku tak mampu berkata-kata. Terlampau khusyuk menyimak, barangkali. Aku tak ingat apa yang melintas dalam pikiranku usai mendengar kisah tersebut. Yang masih kuingat yakni senyumnya yang terlihat aneh bagiku usai Nurman Gendung menandaskan kisahnya. Ya, tidak salah lagi; seulas senyum yang kulihat untuk pertama dan terakhir kalinya setelah seorang rekanku mengabari kematiannya pagi tadi. Kematian kedua yang ia lakukan dengan menggorok lehernya sendiri. (*)
--------------------------
MUHAMMAD LUTFI MAULA


Penulis lahir di Jakarta 08 Februari 2000. Pembaca buku. Menulis esai, cerpen, puisi dan resensi buku. Kini bermukim di Serang, Banten.