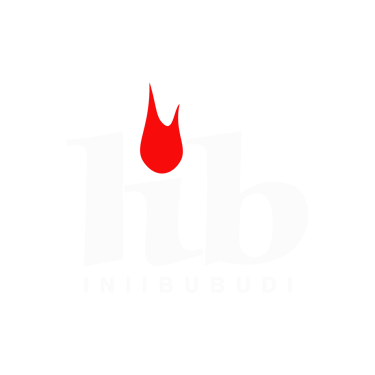Putut Pasopati dan Ingatan yang Ditebar
ESAI
Oleh: Imam Khanafi
8/29/2025


DI TENGAH kesibukan arus globalisasi yang terus mendorong seni rupa ke arah pasar dan sensasi, karya Putut Pasopati—seniman asal Pati, Jawa Tengah—hadir sebagai suara lirih yang mengingatkan manusia akan kedekatannya dengan alam dan ingatan masa kecil. Ia tidak menempatkan seni rupa sekadar sebagai objek konsumsi visual, melainkan sebagai artefak pengalaman: jejak-jejak yang lahir dari tubuh, lingkungan, dan spiritualitas.
Saya menulis esai ini karena sebuah kegelisahan yang pelan-pelan tumbuh dari obrolan dan perjumpaan saya dengan Putut Pasopati, 30 Agustus 2025 malam, dalam ruang pamerannya. Ada semacam keakraban yang membuat saya tidak hanya melihat karyanya sebagai benda seni, melainkan juga sebagai pantulan dari dirinya yang resah, lirih, dan jernih. Apa yang diucapkan Putut tentang hidup hari ini—tentang alam, masa kecil, dan ingatan—seakan menggema di dalam diri, menuntut untuk dituliskan.
Di Balai Budaya Rejosari, Kudus, akhir Agustus 2025, ruang seni seolah menjadi ladang pertemuan antara kata dan warna. Pameran bertajuk “Teks Merupa, Merupakan Teks” menghadirkan karya rupa Putut Pasopati yang bersanding dengan puisi-puisi Arif Khilwa dan Aloeth Pati. Acara ini menjadi bagian dari tradisi Ngangsu Banyu, sebuah rangkaian yang tidak sekadar merayakan kreativitas, melainkan juga merawat ingatan dan spiritualitas lokal.
Putut Pasopati, seniman asal Pati yang kerap mengolah jejak masa kecil dan lanskap sosial ke dalam kanvas, kali ini membiarkan puisinya datang dari luar dirinya. Sapuan warna, tekstur, dan bentuk yang ia hadirkan tidak berdiri sendiri, melainkan berdialog dengan bait-bait puisi. Di sini, teks menjelma rupa, dan rupa justru menemukan artikulasinya lewat teks. Simbiosis inilah yang membuat pameran terasa segar: pengunjung tidak hanya membaca atau melihat, melainkan turut menafsir, menyusun ulang makna, dan merasakan pergeseran bahasa menjadi gambar serta gambar menjadi bahasa.
Rangkaian acara 29–30 Agustus itu tidak berhenti pada pameran visual. Pertunjukan seni, dialog budaya, hingga workshop menulis puisi dan menggambar membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Seni rupa tidak lagi berada di balik dinding galeri; ia keluar, bercampur, dan berbagi energi dengan kata serta tubuh-tubuh yang hadir.
Pameran ini mengingatkan bahwa seni, pada dasarnya, adalah medium lintas batas. Ketika teks dan rupa dipertemukan, lahirlah wilayah permenungan baru: seni yang bukan hanya dilihat atau dibaca, tetapi juga dialami sebagai peristiwa bersama.
Ingatan tentang Putut
Ada sesuatu yang selalu kembali ketika kita berhadapan dengan karya Putut dalam pameran bertajuk Nyebar Wineh. Karya-karya itu seolah bukan sekadar lukisan atau dekorasi visual, melainkan benih—wineh—yang ditanamkan di dalam ingatan. Benih itu, seperti pengalaman masa kecil yang sederhana, perlahan tumbuh di lapisan waktu, menghadirkan kembali suasana yang pernah akrab: aroma sawah yang lembap, suara jangkrik di malam hari, permainan anak-anak di pematang, hingga kesunyian desa yang seringkali hanya bisa dikenang.
Putut, dengan caranya, menjadikan seni sebagai ladang di mana benih-benih ingatan itu ditebar. Ia tidak sedang meniru realitas, melainkan menghadirkan simbol yang bisa dirasakan kembali oleh siapa pun yang menatapnya. Susanne Langer, seorang filsuf seni, pernah mengatakan bahwa seni bukanlah tiruan kenyataan, melainkan simbol presentasional dari “perasaan hidup” (presentational symbol of felt life). Pandangan ini tampak begitu dekat dengan karya-karya Putut. Garis, warna, dan motif lokal yang ia gunakan bukanlah hiasan semata, melainkan bahasa—bahasa yang memungkinkan pengalaman personal bertemu dengan kearifan kolektif.
Bagi Putut, barangkali seni adalah cara merawat ingatan. Ia merangkai masa lalu yang rapuh menjadi tanda-tanda visual yang bisa dibaca ulang. Motif-motif itu, yang bersumber dari pengalaman tubuh dan ruang desa, seakan menyimpan pesan bahwa masa kecil tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk disemai kembali, agar tumbuh sebagai pengalaman bersama.
Maka Nyebar Wineh dalam ingatan saya bukan sekadar pameran. Ia adalah ajakan untuk menengok masa lalu, untuk menyadari bahwa apa yang kita sebut “ingatan” bukan hanya milik pribadi, melainkan juga bagian dari sebuah kebudayaan. Di situlah karya Putut menemukan maknanya: ia menjadikan seni sebagai ladang simbol, tempat ingatan personal bertaut dengan pengalaman kolektif, dan tempat benih-benih itu tumbuh melampaui waktu.
Putut Pasopati menyebut dirinya sebagai “ArtWorker”. Identitas ini penting karena memposisikan seniman bukan sebagai “genius individual” yang berdiri jauh di atas masyarakat, melainkan sebagai pekerja yang bekerja dengan ingatan, artefak, dan realitas sosial. Di sini terasa gema Theodor W. Adorno, yang mengingatkan bahwa seni sejati lahir sebagai negasi terhadap industri budaya. Putut menghadirkan karya yang tidak tunduk pada kapitalisasi estetika, melainkan mencoba mendokumentasikan sesuatu yang lebih rapuh—masa kecil, permainan, benda sederhana, atau relasi manusia dengan air dan tanah.
Seni baginya adalah arsip tubuh yang bergerak. Karya bukanlah penjara memori, tetapi jalan agar memori itu tetap hidup. Seperti air yang terus mengalir, karya Putut menolak untuk membatu. Ia menghadirkan lukisan, instalasi, atau pameran kolaboratif sebagai ruang cair, tempat masyarakat bisa menyelami pengalaman bersama.
Ngangsu Banyu: Ritual Air sebagai Estetika
Keterlibatan Putut dalam tradisi budaya seperti Ngangsu Banyu di Gunung Segoro Rejosari menambah lapisan filsafat dalam seni yang ia jalani. Ngangsu Banyu bukan hanya ritual mengambil air dari mata air, melainkan tindakan estetik kolektif. Proses berjalan ke mata air, menimba, lalu membawa pulang air, adalah peristiwa performatif yang menciptakan makna: bahwa air adalah sumber hidup, pengikat masyarakat, dan simbol keselamatan.
Jika dilihat dengan kacamata Merleau-Ponty, tubuh manusia dalam tradisi ini tidak sekadar menjadi pelaku, melainkan medium persepsi. Gerakan menimba air, menciduk, dan membawanya pulang adalah gestur fenomenologis—gerak yang memanggil kesadaran bahwa manusia selalu sudah berada di dalam dunia, menyatu dengan tanah, bebatuan, dan sumber air. Seni rupa Putut, yang banyak terinspirasi alam, tampak menjadi gema visual dari pengalaman tubuh kolektif ini.
Lebih jauh, Ngangsu Banyu mengandung dimensi etis sebagaimana dibicarakan oleh Jacques Rancière: seni (atau ritual) dapat mengatur ulang “pembagian yang bisa dirasakan” (distribution of the sensible). Air, yang dalam kehidupan modern dianggap sekadar komoditas (dijual dalam botol plastik), dalam ritual ini ditempatkan kembali sebagai sesuatu yang sakral dan bersama. Inilah politik estetika: menggeser persepsi kita tentang air, dari sekadar benda konsumsi menjadi sumber kehidupan yang harus dirawat.
Jika teori Barat memberi kerangka kritis, maka filsafat Timur memberikan napas yang lebih dalam pada praktik Putut Pasopati. Dalam kosmologi Jawa, air (banyu) selalu diasosiasikan dengan kesuburan, ketenteraman, dan keseimbangan kosmos. Ungkapan “urip iku mung mampir ngombe” mengandaikan bahwa hidup manusia hanyalah singgah sebentar untuk meneguk air. Air adalah penanda perjalanan, dan perjalanan itu sendiri adalah pengalaman estetis.
Di titik ini, karya Putut yang menggabungkan alam dan spirit dapat dibaca sebagai estetika keheningan: upaya mengajak masyarakat untuk berhenti sejenak, merasakan kembali bagaimana dunia yang sederhana—air, tanah, sawah, batik, warna cerah—menyimpan filsafat hidup. Ia mengingatkan bahwa seni bukan hanya soal visual, tetapi tentang cara manusia menempatkan diri di dalam jagat.
Putut Pasopati dan tradisi Ngangsu Banyu sama-sama menegaskan bahwa seni dan budaya memiliki fungsi vital: menjaga keseimbangan hidup. Seni rupa tidak berhenti pada kanvas, tetapi mengalir seperti air ke dalam kehidupan sosial, spiritual, dan ekologis. Dalam kerangka ini, Putut tidak hanya seorang seniman, tetapi juga seorang penjaga memori kolektif, pengingat bahwa ingatan masa kecil, artefak budaya, dan alam harus terus dirawat melalui seni.
Seperti air yang ditimba dari sumber di Gunung Segoro Rejosari, karya-karya Putut adalah sumber makna yang tak pernah kering. Ia mengalir, menyegarkan, sekaligus mengingatkan kita bahwa tanpa air—tanpa seni, tanpa ingatan—hidup hanyalah gurun yang tandus. Semoga bermanfaat. (*)
--------------------------
IMAM KHANAFI
Pegiat literasi dan pengamat seni pertunjukan, tinggal di Kudus.


Putut Pasopati dengan beberapa karyanya pada Pameran Puisi Rupa "APA", yang berlangsung Balai Budaya Rejosari, Agustus 2025. (dok: Ist)