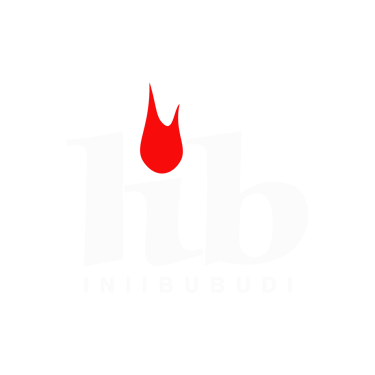Srowot dan Jembatan yang Tak Pernah Sampai
CERPEN
Karya: Basuki Fitrianto
10/1/2025


SETIAP PAGI, sebelum matahari sempat menyodok Monas dengan hangatnya, Srowot sudah duduk di bawah tiang penyangga JPO baru yang masih dibungkus baliho iklan minuman teh botolan. Ia menggelar tikar kumal bertuliskan “Selamat Datang di Jakarta” hasil rampasan dari spanduk kampanye caleg gagal tahun 2009.
“Katanya ini JPO futuristik,” gumam Srowot sambil menyalakan rokok lintingannya. “Tapi aku masih kencing di selokan.”
Orang-orang lalu-lalang di bawah jembatan, menengadah sejenak melihat tangga spiral dan lampu LED berkedip-kedip seperti diskotik. Tapi tak satu pun dari mereka benar-benar naik. Tangga belum dipasang. Liftnya terkunci. Dan pintu masuk masih dipagari seng.
“Jembatan ini bukan untukmu, Rowot,” kata satpam berperut tambun ketika Srowot pernah mencoba naik waktu malam. “Ini untuk warga kota.”
Srowot tertawa terpingkal-pingkal waktu itu. Warga kota? Lantas ia ini apa? Fosil?
Ia sudah tinggal di Jakarta sejak Presiden masih mengenakan jas safari dan wartawan masih pakai kamera dengan lampu flash sebesar radio. Srowot tahu persis letak tiap lubang trotoar, tiap tiang lampu yang nyetrum, bahkan tahu titik mana yang paling cepat mengering habis hujan. Tapi kini, orang-orang bicara tentang kota pintar, jembatan instagenik, dan trotoar bersensor.
Srowot pernah mencoba naik JPO di Blok M dua bulan lalu. Tapi ia tersandung karena salah satu ubin kaca yang katanya tembus pandang, ternyata tembus ke neraka. Ia meluncur, menabrak pagar besi, dan kencing berdiri dua hari akibat tulang ekor miring.
“Jembatan-jembatan ini terlalu pintar untuk orang bodoh seperti aku,” katanya pada seekor kucing belang tiga yang tiap malam menyusup ke kantong plastiknya.
Jakarta memang sedang gila jembatan. Dalam sebulan, lima JPO dibangun. Yang satu bentuknya seperti pisang rebus, yang lain mirip tentakel. Ada yang warnanya merah muda menyala, konon agar bisa tampil di sinetron. Tetapi di gang sebelah tempat Srowot biasa mengamen, jembatan bambu yang menghubungkan anak-anak ke sekolah sudah raib separuhnya. Dicuri atau dimakan waktu, tak ada yang tahu.
“Kalau jembatan itu viral, mungkin dibetulin,” kata seorang ibu penjual gorengan. “Atau difoto dulu sama pejabat.”
Minggu lalu, Srowot melihat anak kecil jatuh ke kali karena mencoba meniti jembatan dari dua papan licin. Ia terjun ke air, mengangkat bocah itu, lalu duduk berdua sambil menunggu kering. Anak itu bertanya, “Om tinggal di mana?”
“Di Jakarta,” jawab Srowot.
“Jakarta yang mana?”
Pertanyaan itu membuat Srowot terdiam.
Ia pernah tinggal di kolong jembatan yang dibongkar karena dianggap sarang gelandangan. Ia pindah ke halte yang kemudian ditutup karena proyek revitalisasi. Lalu sempat tidur di taman kota, yang kini diubah jadi ruang terbuka hijau premium dengan pagar dan CCTV.
Jakarta membangun begitu cepat, tapi Srowot merasa ditinggal. Seperti jembatan yang menghubungkan dua dunia, tapi tidak menyisakan satu pun anak tangga untuknya.
“Besok katanya diresmikan,” kata petugas berseragam, menunjuk JPO di atas mereka. “Wali Kota mau datang. Biar orang tahu Jakarta ini maju.”
“Maju terus sampai kami ketinggalan,” sahut Srowot pelan.
Malamnya, hujan turun. Srowot berlindung di bawah jembatan, bersama kantong plastik berisi sandal bolong, sepotong roti, dan potret buram dirinya saat masih punya KTP.
Ia menatap lampu warna-warni di jembatan. Indah. Seperti pelangi. Tapi tak bisa disentuh. Tak bisa ditinggali. Tak bisa dikencingi.
Jakarta seakan membangun langit, tapi lupa bumi.
Dan Srowot, masih di bawah sana. Menunggu jembatan yang benar-benar membawanya pulang.
Pagi harinya, kota dibungkus warna perak. Kabut tipis menyelimuti jalanan, menumpuk di sela-sela trotoar granit. Bau cat baru dan plastik pembungkus menyengat dari JPO yang hendak diresmikan. Bendera-bendera kecil dipasang tergesa. Para petugas sibuk menyapu dedaunan, menyiram jalan, dan menyusun kursi lipat berlapis kain satin. Jakarta bersiap menyambut pejabat yang datang dengan dasi dan pidato.
Srowot masih di tempatnya. Kini mengenakan kemeja putih yang digulung di ujung lengan—sumbangan dari entah siapa, entah tahun berapa. Ia mencuci kemeja itu dengan air got semalam, dan menggantungnya di pagar jembatan sampai kaku.
“Gue harus tampil rapi kalau mau nonton peresmian,” katanya kepada seekor kecoa yang lewat di depannya.
Sekitar pukul sembilan, iring-iringan mobil hitam datang. Orang-orang bersorak. Seorang pria tinggi berkacamata gelap turun, melambai kepada kamera. Wartawan mulai menyorot. Pembawa acara menyebut-nyebut kata “transformasi kota”, “aksesibilitas urban”, “ruang aman bagi pejalan kaki”—sebuah orasi yang terdengar lebih seperti lirik lagu yang tak pernah dinyanyikan di jalan tempat Srowot hidup.
“Bapak, JPO-nya keren sekali,” kata seorang wartawan muda.
“Iya dong,” jawab pejabat itu. “Ini bukan sekadar jembatan. Ini simbol kemajuan. Ini tempat warga berinteraksi, berfoto, beraktivitas!”
Srowot melambaikan tangan. “Pak! Pak! Saya mau tanya!”
Pejabat menoleh. Kameramen menyorot. Srowot melangkah maju dengan semangat seperti anak-anak naik panggung lomba menggambar.
“Saya mau tanya, Pak. Kalau ini jembatan buat rakyat, kenapa pagar masuknya dikunci?”
Suasana hening sejenak. Pejabat tertawa kaku. “Itu... karena belum diresmikan. Nanti juga dibuka.”
“Tapi saya butuh lewat sekarang, Pak,” sahut Srowot. “Saya bukan mau selfie. Saya mau nyebrang. Trotoar seberang jebol. Jalan putarannya jauh. Kalau nyelonong, ditabrak angkot. Jadi jembatan ini buat saya juga, kan?”
Pejabat menoleh pada ajudannya. Ajudan menoleh pada satpam. Satpam menatap Srowot seakan ia penyakit yang bisa menular.
“Kamu tinggal di mana?” tanya pejabat.
Srowot menunjuk ke bawah jembatan. “Situ.”
Pejabat mengerutkan alis. “Maksudnya... tinggal?”
“Iya, Pak. Di Jakarta. Di ibu kota. Di bawah jembatan ini.”
Terdengar suara batuk dari pembawa acara. Musik latar berhenti. Wartawan menunduk. Seorang petugas buru-buru mematikan mikrofon.
Pejabat itu tersenyum kaku. “Baik, kita lanjut potong pita dulu ya.”
Srowot berdiri terpaku. Bendera-bendera kecil berkibar pelan di angin, seakan mengejek.
Ketika pita dipotong, balon-balon warna biru dan merah naik ke langit, bersama harapan-harapan yang tak pernah mampir di tanah. Lift jembatan dibuka. Para wartawan naik, para pejabat naik, lalu berfoto di atas dengan latar belakang langit Jakarta yang samar.
Srowot duduk lagi di bawah, persis di tempatnya semula. Beberapa menit kemudian, ia melihat seorang ibu tua mencoba menyeberang di bawah jembatan. Jalur itu bukan zebra cross. Mobil melaju cepat. Ia hampir disambar, tapi ditarik oleh pemuda berjaket ojek daring.
“Bu, jangan di situ! Itu bahaya!”
“Tapi saya nggak bisa naik tangga. Mana liftnya ngunci,” jawab si ibu.
Srowot berdiri. Ia menatap jembatan itu lagi. Kini benar-benar dibuka. Tapi hanya bisa dinaiki dari sisi timur. Sisi barat masih dipagari seng, karena tukang proyek belum selesai pasang ubin. Lift macet lagi. Tangga spiralnya terlalu curam. Ibu itu memilih balik kanan.
Tak lama kemudian, Srowot melihat tiga anak berseragam sekolah meniti rel trotoar rusak di ujung jalan. Mereka memilih menerobos karena takut telat sekolah. Tapi di tengah jalan, salah satu dari mereka terpeleset. Ia jatuh, kepalanya membentur aspal. Sepatu sebelah terlempar.
Srowot lari menghampiri.
Orang-orang berdiri, menonton, tapi enggan turun tangan.
Srowot mengangkat anak itu, yang kini menangis, lalu menuntunnya ke pinggir. Ia memungut sepatu si bocah, lalu duduk di trotoar.
Wartawan yang tadi mewawancarai pejabat menoleh. Ia diam sejenak, lalu mengangkat kameranya, mengabadikan punggung Srowot yang mendekap anak itu.
Sore harinya, foto itu viral. Judulnya: “Potret Rakyat Kecil dan Jembatan yang Terlupakan”. Sebagian orang memuji. Sebagian lain mengecam. Tapi malamnya, Srowot tetap tidur di bawah jembatan yang kini bercahaya seperti pusat galaksi.
Keesokan harinya, pagar seng di sisi barat jembatan masih belum dibuka. Lift masih macet. Tangga masih terlalu curam untuk lansia. Tapi lampunya tetap menyala. JPO itu tetap jadi latar selfie, simbol kemajuan.
Srowot duduk di trotoar dengan kopi instan yang diseduh dari air dispenser pom bensin. Di seberangnya, seorang anak muda mendekat, lalu duduk di sebelahnya.
“Om yang di foto itu ya?”
Srowot mengangguk pelan.
“Hebat, Om. Jadi pahlawan jalanan.”
Srowot tersenyum kecil. “Ah, bukan. Pahlawan itu yang bisa bikin jembatan sampai ke hati orang. Saya cuma numpang tidur.”
Anak muda itu terdiam. Kemudian berkata, “Om mau saya beliin roti?”
“Kalau ada,” jawab Srowot, “tapi jangan lupa beliin juga untuk jembatan. Kasihan, dia lapar perhatian.”
Langit Jakarta mulai gelap. Lampu-lampu menyala, tapi jalanan tetap bolong. Trotoar tetap berlubang. Dan JPO—yang katanya dibangun untuk semua orang—tetap hanya bisa dinikmati dari layar ponsel.
Di bawah jembatan, Srowot memandangi langit malam. Tak berharap banyak. Hanya bertanya-tanya dalam hati, berapa jembatan lagi yang akan dibangun, sebelum satu pun benar-benar sampai padanya.
---
Surakarta, 2025
--------------------------
BASUKI FITRIANTO
Pria kelahiran Yogyakarta lulusan SMKI Jogja jurusan teater ini, sekarang tinggal di Surakarta.