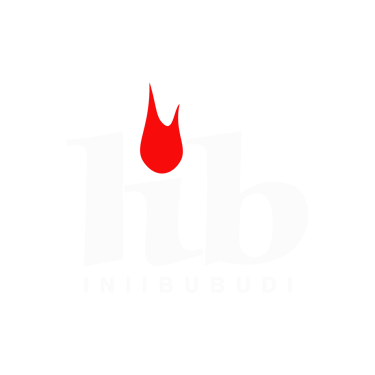BHUMI, Luka-luka yang Menghidupkan
BUKU
Oleh: Asa Jatmiko
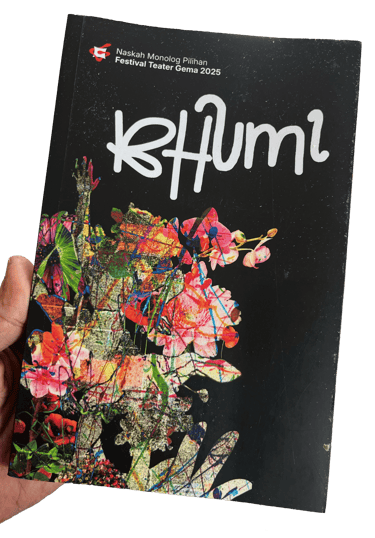
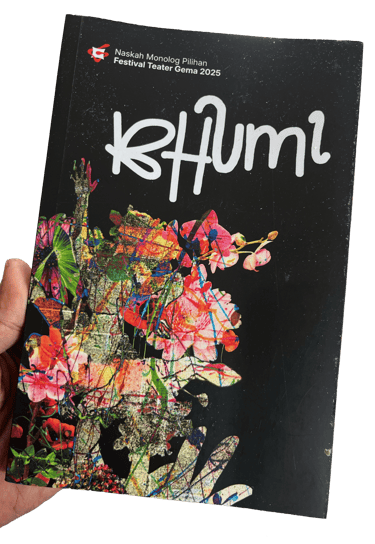
BARANGKALI jaman memang telah berubah. Dan saya semakin yakin akan hal itu, manakala saya membaca 25 naskah monolog yang dikirim Panitia Sayembara Naskah Monolog Teater Gema tahun 2025. Naskah-naskah monolog yang menyuarakan realitas sosial yang sangat kental, mendedah kepribadian-kepribadian tangguh yang terlipat oleh berbagai persoalan sosial, sosial media, yang luput dari perhatian, dan juga teriakan-teriakan sunyi yang mencakari langit malam. Naskah monolog, pada saat ditulis, sangat melekat dengan bagaimana pandangan dan pemikiran penulisnya kepada satu sosok, satu pribadi, yang “berjuang berdarah-darah” atas kesulitan yang dihadapinya. Maka bisa dipahami bahwa naskah monolog merupakan tawaran pemikiran dan renungan seorang penulis akan persoalan hidup seseorang (tokoh) yang ditulis dengan sangat subyektif, dan karena itulah menjadi sangat khas.
Dalam naskah “Surup”, terkurung dalam sebuah ruangan asing, seorang ibu dari Tarno yang hilang saat surup (waktu senjakala), mengatakan, “mereka mengurungku hanya karena aku sering, sering bercerita tentang Tarno. Aku hanya ingin mengenang tawa anakku, apa itu sebuah dosa besar?” Ia dianggap gila dan dikurung, padahal menurutnya, “orang gila adalah orang yang tidak memiliki kepedulian! Mereka yang memiliki rasa empati rendah! Mereka yang hanya peduli pada ketenangan desa mereka sendiri! Mereka rela mengorbankan keadilan dan nyawa orang lain demi ilusi damai yang mereka ciptakan!”
Surup, telah menjadi alasan untuk menutupi keengganan warga masyarakat membantu mencari Tarno, anaknya. Bagi ibunya Tarno, ia tidak lagi melihat kepedulian orang lain berdasarkan peri-kemanusiaan. Bahkan “melegalkan” kebohongan seolah-olah jawaban dusta itu sudah cukup menjawab setiap persoalan. Ia tidak melihat aksi nyata, kecuali basa-basi. Ia tidak melihat ada niat peduli, kecuali memaksakan mitos untuk dipercayai secara buta. Alih-alih bersimpati, mereka malah mencapnya orang gila, dan mengurungnya. Kerinduan kepada anaknya, kerinduan yang tak berkesudahan. Persis, kerinduan akan kembalinya hati nurani; membantu sesama tanpa melihat orang apalagi imbalan.
Monolog “Surup” memiliki kekuatan pada tema, tokohnya kuat, peristiwa dan properti yang dipilih juga sekaligus merupakan petanda (simbolik). Struktur dramatiknya baik. Di dalam rangkaian peristiwa kilas-balik yang diceritakan diatur dalam alur yang maju dan semakin meningkat. Apa yang menjadi titik pusat perhatian tokoh dapat tercapai, “dimana kepedulian kalian?! Apakah hanya karena kami tidak punya uang?! Dimana letak hati nurani kalian?! Kalian menyalahkan waktu! Menyalahkan Surup! Seolah-olah Surup adalah dewa kematian! Padahal Surup hanyalah alasan kalian untuk bersembunyi dari dosa!” Kita barangkali juga sering menyalahkan waktu, mengkambinghitamkan waktu, padahal nurani kita sendiri yang telah “terkurung nafsu”.
Ungkapan yang lebih menarik untuk menggambarkan bagaimana cara berpikir orang-orang melalui cara berpikir tokoh terhadap “Ember”. Naskah ini mendeskripsikan dengan cukup lengkap bagaimana sesuatu yang sama (baca: sama wujud, dan juga sama esensi) memiliki tafsir dan diyakini secara berbeda-beda. Sudut pandang ini sangat menggejala pada kehidupan sosial saat ini. Bukan kebendaannya yang berubah, namun perspektif.
Dunia hari ini mengarahkan setiap kepala kepada tangkapan perspektif. Kebenaran mutlak dan esensial, justru menemui kegagapan ketika berhadapan dengan perspektif. Bahkan semakin banyak orang mempercayai, bahwa perspektif itulah kebenaran itu sendiri. Sama halnya dengan pertanyaan si tokoh, “tapi bagaimana cara melepaskan suara? Bagaimana cara melepaskan tawa? Bagaimana cara melepaskan kenangan yang bahkan tidak punya bentuk tapi lebih nyata dari semua ember di dunia ini?”
Kenangan mewujud, dan ember menyusup sebagai ingatan. Demikian juga dengan hati, “semua orang punya ember. Cuma sebagian orang menyebutnya "hati". Sebagian menyebutnya "jiwa". Sebagian menyebutnya "diri". Tapi pada dasarnya... (mengangkat satu ember)... pada dasarnya kita semua cuma ember.” Dengan gaya ungkap tokoh yang aneh dan cenderung lucu (getir?), monolog ini semakin menarik karena apa yang sesungguhnya ingin dihadirkan adalah perspektif dan ambiguitas yang berkelindan dengan kejiwaan manusia. “Ember” telah membawa tokoh mengungkapkan berbagai peristiwa dan perspektif, sebuah kondisi yang menggejala kehidupan kita hari ini.
***
Dengan kekuatan naskah monolog masing-masing, secara umum adalah suara-suara dari para tokoh yang tercekat, tersumbat, tertahan dan menemui kebuntuan akibat tatanan sosial yang “berubah”. Melalui monolog-monolog tersebut, sekaligus juga mereka (para penulis) ingin memberikan “peringatan” bahwa seharusnya ada yang tidak perlu ikut berubah. Yakni: kasih sayang, kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai ini pada gilirannya merupakan mercusuar bagi setiap manusia ketika berlabuh menempuh laut kehidupan. Dengan mengangkat realitas sosial yang dekat dengan pengalaman hidup sehari-hari saat ini, pada beberapa naskah monolog ini secara memiliki kebaruan dalam cara ungkap tokoh mendedahkan kisahnya yang menggigit namun tetap segar.
Dalam naskah monolog yang berjudul “Penggal”, tokoh memanggil-manggil ayahnya yang tak akan pernah kembali. Ia hanya mendapatkan tubuh ayahnya yang tidak lengkap; tanpa kepala. Kekuasaan dan alat kuasa, tahu benar bahwa untuk membungkam warganya yang dianggapnya berbahaya adalah dengan cara membungkamnya, menghentikannya berpikir, dan otak ada di bagian tubuh yang bernama kepala. Mereka telah memenggalnya.
“Kapan keadilan akan datang, Anak?” Suara itu menjadi suara yang terus diteriakkan. “Dimana keadilan?”Bahkan hanya untuk menggelar pertunjukan, penguasa sudah amat ketakutan. Naskah ini mengingatkan kita bagaimana rasa keadilan itu merupakan sesuatu hal yang sangat berarti bagi kehidupan. Tercabiknya keadilan, jelas berasal dari kesewenang-wenangan. Kemudian tokoh menguraikan bagaimana represifnya “puluhan lelaki berbadan kekar” itu, hingga berpuncak ketika “aku teman ayahmu. Aku ingin menunjukkan ini. Aku punya potongan rekaman suara, yang mungkin bisa menjadi barang bukti atas kasus yang selama ini ditutupi.”
Perlahan, dengan tangan gemetar, lelaki itu memutarkan rekaman suara dari ponselnya. Samar-samar, terdengar dari rekaman itu: Penggal!!! Dan ternyata belum usai. Lelaki yang membawa titik terang itu, mati ditembak tepat di hadapanku.
Monolog ini membeberkan tokoh yang juga seorang aktivis, dalam pencarian panjang ayahnya, kerinduan dan rasa cintanya kepada ayahnya, dalam sudut pandang seorang perempuan. Alur dramatiknya baik, disusun perlahan menuju klimaks yang semakin meneror, semakin memperjelas kesewenangan penguasa dalam membungkam semua yang dianggap “sensitif” terhadap negara.
Satu hal lagi yang penting untuk disampaikan di sini, keragaman tema yang diangkat pada naskah-naskah yang masuk menunjukan juga keragaman konsep naskah yang dipilih. Ada yang berkonsep realisme, surealisme dan absurd dalam sekumpulan naskah monolog ini. Tentunya ini sangat menyenangkan, dan kita bisa berharap banyak dari sini akan muncul penulis naskah lakon (monolog dan teater) yang melahirkan karya-karyanya dengan lebih baik lagi. Tawaran-tawaran yang kaya tersebut akan merangsang tafsir sutradara dan aktor monolog, menggali dan memaknai lebih dalam, manakala naskah-naskah ini dimainkan.
Absurditas tokoh dimunculkan dalam “Jiwa yang Hilang”, antara janin/bayi dan ibunya. Pergulatan janin/bayi di dalam perut ibunya “terdengar” dengan begitu jelas. Naskah ini sangat menarik dan akan memancing pertunjukan monolog eksperimental dengan sudut pandang penggarapan masing-masing, baik dari keaktoran, seting dan properti dan juga eksplorasi gagasan janin yang telah berpersona, memiliki pikir dan rasa. Gagasan tokoh menjadi janin/bayi, adalah hal rumit, namun sesungguhnya justru “pintu eksplorasi” yang bisa mengantar pada paradigma yang lebih luas mengenai makna “hidup” dan “berdetak”.
“Sebenarnya apa yang berada di luar sana? Cahaya? Makanan yanglebih enak? Atau hanya ruangan gelap dan lembab lainnya tetapi lebih luas? Jika hanya ruangan gelap dan lembab, aku lebih memilih tinggal di sini,” saya cuplik sebagai contoh. Dengan keterangan seting yang ditulis demikian, “TERLIHAT LATAR SETTING MENYERUPAI BEBERAPA ORGAN DI DALAM PERUT IBU YANG SEDANG HAMIL. BEGITU JUGA DENGAN DINDING-DINDING YANG BERWARNA MERAH. SEORANG WANITA SEDANG BERPOSE SEPERTI JANIN YANG BERADA DI DALAM PERUT.”
Konsep ini menjadi contoh bagaimana terobosan-terobosan gagasan yang berani, kemudian diekspresikan. Memuat nilai yang lebih kompleks, tidak sekadar bagaimana hubungan janin dengan ibunya, namun juga “keseharian” janin yang mampu mendengar berbagai peristiwa “di luar ruangannya”, terutama yang menyangkut ibunya. Tragisnya, monolog ini berakhir pada saat janin itu mengatakan, “Di sinilah aku berakhir. Dunia yang lebih damai. Tak sempat aku mendengarnya bernyanyi, tak sempat aku melihat dengan baik indah rupanya, tak sempat aku menyaut panggilan-panggilannya.” Ia tidak hadir menjadi bukti cinta, tetapi ia tahu kepada siapa berterimakasih. Ialah ibundanya.
Dan eksplorasi seting properti juga ditawarkan dalam naskah monolog yang berjudul “Aiaia”. Dengan memajang kaca-kaca persegi yang memenuhi ruangan, tak ubahnya keseharian orang yang hidup di tengah-tengah “layar-layar kaca” dalam segala formatnya; televisi, telepon pintar, cermin, yang secara sadar maupun tidak turut mengendalikan gaya hidup. Tokoh adalah seorang pemeran, penokohan yang pas untuk menggambarkan kesibukan sebelum bermain, saat bermain dan bagaimana saat akan mengakhirinya. Sepertinya bermain, sepertinya kita diajak bermain-main. Tetapi kata tokoh itu, “yang mana? Yang mana layar kaca saya, mu, kalian, mereka, dan kita? Apakah kaca-kaca di ruangan ini atau kaca-kaca di luar sana? Atau kaca-kaca itu kita? Ataukah apa?”
Irama permainan dibuat agak lambat, untuk memberi “jeda” atas ungkapan-ungkapan yang disampaikan tokoh, melompat-lompat dari retorika ke majas-majas, dari realita ke peristiwa-peristiwa imaji, belum lagi kalimat-kalimat bernada filsafat. Tidak mudah untuk disampaikan, namun akan mengena apabila tepat pengungkapannya. Naskah ini pun tak kalah menarik, sekaligus menantang kemampuan keaktoran.
***
Naskah-naskah monolog yang lainnya memiliki kecenderungan yang nyaris sama dengan apa yang telah saya paparkan di atas. Tentu, ini merupakan tanda akan harapan yang besar akan dunia naskah lakon (monolog dan teater) kita ke depan semakin baik. Bahwa masih ada naskah-naskah monolog yang belum baik struktur kalimat dan penulisannya, dan terlebih struktur dramatik naskahnya. Namun jumlahnya sangat kecil, hanya beberapa. Secara umum naskah-naskah monolog telah ditulis memiliki kecenderungan nilai yang baik. Kisah-kisah yang diungkap dalam naskah-naskah monolog ini adalah kisah luka-luka yang menggugah semangat, melecut keberanian, dan menghidupkan pembacanya atau (kalau dipanggungkan) penontonnya dari kelesuan berkarya. Untuk itu saya mengucapkan selamat. Terus bergerak. Terus berkarya. Terus bersuara.
Terimakasih.
Asa Jatmiko,
Kurator
Judul: BHUMI
Naskah Monolog Pilihan | Festival Teater Gema 2025
Penulis: Amelda Apriliana, Aulia Nur Rohmah, Bagus Harry Nugroho, Rahma Widia Sari, Nur Fitria Rohima, Novita Sari, Olive Medina Kesuma, Beni Nada Krisna, Shela Nadine Purwaningsih dan Jodi Setyo Nugroho
Kurator: Asa Jatmiko
Tebal Hal: xvi + 125 hal
Cetakan Pertama: Desember 2025
QRCBN: 62-1695-9599-684
Penyelenggara: Teater Gema
Penerbit: Beruang Cipta Lestari, Semarang