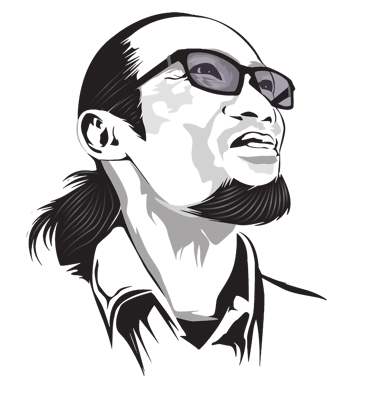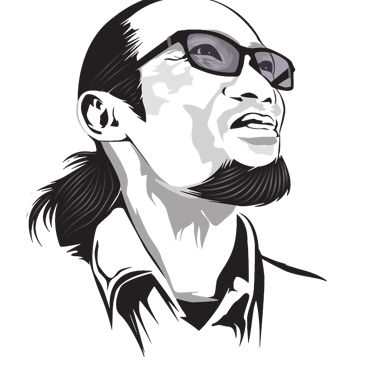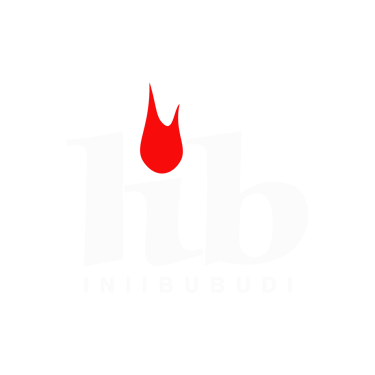Dongeng tentang Sebuah Festival
ESAI
Oleh: Asa Jatmiko
1/2/2026


Pengantar:
Bagaimana sebuah festival teater pelajar yang kemudian dikenal dengan FTP di Kudus itu pada mulanya ada? Apa sebenarnya gagasan utama yang ingin diraih? Berikut ini sebuah tulisan yang disusun oleh Agam Abimanyu dari wawancara tertulis dengan Asa Jatmiko.
___________
GAGASAN Festival Teater Pelajar (FTP) di Kudus tidak lahir dari ambisi membuat perhelatan besar, apalagi dari kalkulasi prestise kebudayaan. Ia tumbuh dari pengalaman lapangan yang sangat konkret: perjumpaan antara teater dan pelajar di ruang-ruang sekolah. Sekitar tahun 2005–2006, saya menggagas program pentas keliling SMA dan SMP di Kudus dengan satu pesan sederhana: berteater itu mudah dan menyenangkan.
Bersama Teater Djarum, kami memainkan naskah-naskah yang relatif ringan dan komunikatif, komedi yang dekat dengan keseharian remaja seperti Sepasang Mata Indah, Hanya Satu Kali, Senja dengan Dua Kelelawar, hingga Ketika Iblis Menikahi Seorang Perempuan. Setelah pentas, kami tidak berhenti di tepuk tangan. Kami duduk, berbincang, dan mendengar. Saat itu, hanya satu dua sekolah yang telah memiliki kelompok teater.
Beberapa tahun kemudian, dampaknya mulai tampak. Sekolah-sekolah menunjukkan minat untuk membuka ekstrakurikuler teater. Pelajar membentuk kelompok secara mandiri. Teater pelajar bermunculan bukan karena instruksi kurikulum, melainkan karena kebutuhan berekspresi. Dari situ muncul pertanyaan yang lebih mendasar: akan dikemanakan aktivitas ini? Apa muaranya?
FTP lahir sebagai jawaban atas kegelisahan tersebut. Sejak awal, festival ini tidak dirancang semata sebagai ajang kompetisi, melainkan sebagai ruang temu, ruang belajar, berbagi, dan saling menguatkan antar teater pelajar. FTP pertama digelar pada tahun 2007 dengan segala keterbatasannya, seperti panggung tratak ala panggung mantenan, lantai gemlodak, namun dengan kesungguhan penuh. Dari kesederhanaan itu, FTP kemudian berkembang menjadi agenda tahunan yang relatif mapan.
Dalam perjalanannya, saya sempat merumuskan jargon berteater itu keren. Pada masa itu, “keren” kerap dilekatkan pada gaya hidup kebarat-baratan, pada citra modern yang sering kali menjauh dari konteks lokal. Teater saya tempatkan sebagai alternatif gaya hidup, bahwa pelajar yang berteater adalah pribadi yang memiliki nilai, daya juang, kepekaan sosial, serta tanggung jawab tanpa harus mengorbankan prestasi akademik.
Lambat laun dampak FTP ternyata tidak berhenti pada pelajar. Di Kudus, gairah berteater di kalangan seniman lokal ikut tumbuh. Banyak di antara mereka terlibat sebagai pelatih, pendamping, bahkan sutradara teater pelajar. Proses kreatif kembali hidup. Kompetisi muncul, tetapi dalam arti yang sehat serta saling memacu kualitas, bukan saling menyingkirkan. Hubungan simbiosis pun terjalin antara seniman, sekolah, dan komunitas.
Menariknya, dalam beberapa kelompok teater pelajar, peran orangtua mulai ikut terlibat. Dari sinilah saya semakin yakin bahwa ekosistem teater yang ideal bertumpu pada tiga pilar: sekolah, siswa, dan orangtua. Ketika ketiganya berjalan bersama, anak-anak memiliki ruang yang lapang untuk tumbuh, bukan hanya sebagai aktor panggung, tetapi sebagai manusia yang utuh.
Seiring perubahan zaman, jargon itu kembali saya perbarui. Kini saya lebih memilih mengatakan: berteater itu cerdas. Anak-anak hari ini, pada dasarnya, sudah “keren”. Mereka menguasai teknologi informasi, media sosial, dan berbagai perangkat digital yang jauh melampaui generasi sebelumnya. Tantangannya bukan lagi soal akses atau gaya, melainkan soal kesadaran.
Di tengah arus informasi yang cepat dan budaya instan, teater menawarkan sesuatu yang semakin langka: proses. Ia mengajarkan kesabaran, kehadiran, dan relasi antarmanusia. Teater melatih kecerdasan intelektual sekaligus emosional dan kemampuan berpikir kritis sekaligus berempati. Dalam pengertian ini, teater bukan sekadar seni pertunjukan, melainkan ruang latihan kewarasan.
Maka FTP hari ini tidak hanya relevan sebagai festival, tetapi sebagai praktik kebudayaan. Ia menjadi ikhtiar kecil namun konsisten untuk mengingatkan bahwa manusia bukan sekadar pengguna teknologi, melainkan makhluk yang perlu terus belajar memahami diri dan sesamanya. Bahwa kecerdasan bukan hanya soal cepat dan canggih, tetapi juga soal bijak dan berbudaya.
Di titik ini, berteater menjadi lebih dari sekadar aktivitas ekstrakurikuler. Ia menjelma sebagai cara membentuk manusia: cerdas otaknya, cerdas emosinya, dan cerdas kemanusiaannya. Barangkali di sanalah teater menemukan tugas kulturalnya dalam pendidikan hari ini yang bukan hanya mengisi panggung, tetapi ikut merawat masa depan. (Penulis: Agam Abimanyu, mentas.id)
--------------------------
ASA JATMIKO
Art Provocateur