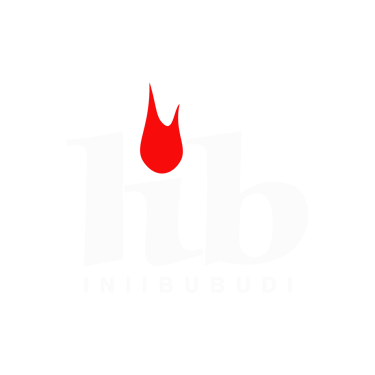Hari Terbaik Bapak
CERPEN
Karya: Pipiek Isfianti
1/1/2026
HARI itu, seusai melaksanakan sholat Shubuh, Bapak bergegas mengambil alat cukurnya dengan begitu hati-hati. Di depan cermin, Bapak mulai bersiap mencukur rambutnya yang sebetulnya belum terlalu panjang. Karena sebulan lalu, Bapak juga sudah mencukurnya sampai habis.
Seperti pagi ini, saat pagi mulai menyiratkan cahaya matahari, Bapak sudah berdiri di depan cermin. Bersiap mencukur rambutnya dengan alat cukur mesin itu. Dengan begitu hati-hati, Bapak mulai mencukur rambutnya sendiri dengan mesin cukur rambut, yang selama ini selalu Bapak simpan dengan rapi di dalam almari. Bapak mengumpulkan rupiah demi rupiah dari hasilnya mengojek untuk membeli alat cukur mesin seharga enam puluh ribu itu.
Aku sendiri, selalu menikmati saat Bapak mulai bersiap hendak mencukur rambutnya. Aku duduk di belakang Bapak, sementara Bapak menghadap ke cermin satu-satunya yang kami punya di rumah peninggalan orang tua Bapak. Aku merasa Bapak juga terasa begitu menikmati saat hendak mulai mencukur rambutnya. Bapak selalu bersuka cita, karena seperti kata Bapak, itu adalah hari terbaiknya. Hari dimana tiap bulan sekali, Bapak bisa bertemu Ibu. Melihat Ibu, memegang tangannya, walau tanpa bisa bicara sepatah kata. Bapak bilang, itulah hari terbaik selama sebulan dalam hidupnya. Hari terbaik yang selalu Bapak tunggu selama hampir lima belas tahun ini.
Ya, sejak Bapak terpisah dari Ibu, Bapak selalu menunggu hari terbaiknya. Satu hari dalam sebulan, dimana Bapak bisa bertemu dengan Ibu.
Aku masih duduk di kursi kayu yang cat pliturnya sudah terkoyak di sana-sini. Dulu lima belas tahun lalu, saat aku masih berusia lima tahun, aku selalu melihat Ibu duduk di situ. Ibuku yang cantik, berkulit putih, dan bermata sipit selalu ribut dengan persoalan rambut Bapak. Ya, Bapak selalu memanjangkan rambutnya. Sebagai seorang pelukis, Bapak merasa lebih nyaman berambut gondrong. Bapak juga terlihat semakin ganteng dan gagah dengan rambut panjangnya yang selalu ia rawat dengan baik selama ini.
Tapi itu dulu, lima belas tahun lalu, sebelum sebuah kejadian yang mengguncang jiwa kami, terutama jiwa Bapak terjadi. Saat suatu pagi, kami tidak mendapati Ibu di kasur kapuk kami yang tipis. Juga di dapur kami yang begitu sederhana, juga di kamar mandi kami yang dindingnya terbuat dari kayu dan bolong sana-sini. Di seluruh isi rumah reyot kami, Ibu tak bisa kami temukan. Suatu peristiwa yang telah mengubah hidup kami. Menghancurkan hati dan jiwa kami.
Aku kibaskan kepalaku kuat, kutarik napas panjang, berusaha membuang semua ingatan itu. Kembali menatap Bapak yang sedang duduk tegak di depan cermin. Satu hari di tiap bulan di hari terbaiknya. Hari yang selalu Bapak tunggu di sepanjang hidupnya, sejak lima belas tahun lalu. Sejak aku berusia lima tahun, sampai sekarang usiaku dua puluh tahun. Sejak aku TK sampai kemarin aku lolos seleksi jalur undangan di kampus negeri favorit di kotaku. Kampus tempat ibuku juga kuliah dulu, meraih gelar sarjana pendidikannya, menjadi guru sekolah swasta terbaik di kotaku. Sampai ibu ketemu Bapak. Mereka saling jatuh cinta. Walau tentu saja, sangat banyak perbedaan keduanya. Ras, keyakinan, ekonomi, segalanya. Tapi mereka memilih tetap bersama. Sampai aku lahir, sampai Bapak harus rela lukisan demi lukisannya dijual murah untuk hidup kami bertiga. Sampai kemudian hari itu, Ibu tak ada lagi di rumah kami.
Aku dan Bapak sejak hari itu terus mencari Ibu. Menuju rumah besar Ibu di Pecinan yang tembokknya begitu tinggi. Bapak memencet bel rumah yang katanya rumah Engkong dan Emakku, orang tua ibuku itu, walau aku tak pernah sekalipun bertemu mereka. Dari pagi sampai siang, Bapak terus berada di depan rumah berpagar tembok besar itu, tapi tak sedikit pun pintu pagarnya terbuka. Tiap hari Bapak selalu datang ke rumah besar itu, kadang bersamaku, tapi ketika aku sekolah, Bapak datang sendiri. Tubuh Bapak yang dulunya tegap, kini menjadi kurus kering. Mata Bapak semakin cekung dan menghitam. Tapi Bapak tak pernah berhenti mengajarku belajar, mengantarku sekolah, dan bekerja apa saja agar aku terus sekolah.
Sampai hari itu, hari terbaik dalam hidupnya, saat Bapak menunggu di depan rumah besar bertembok tinggi itu, Bapak melihat rombongan para biksu dengan jubah kunyitnya. Kepala mereka yang polos dan bersih berjalan beriringan menuju rumah besar yang dibuka perlahan. Bapak bergegas mengikuti rombongan para biksu itu. Yang berjalan terus menuju lorong-lorong rumah milik Engkong dan Emakku. Rombongan itu menuju kamar besar di ruang belakang.
Para biksu maju satu persatu bergiliran, mendoakan sosok yang berbaring lemah di sana. Dada Bapak membuncah. Bapak melihat Ibu yang terbaring lemah, tubuh yang tinggal tulang-belulang, wajah yang layu tanpa jiwa. Bapak menyerobot antrian para biksu. Bapak berteriak, menyebut nama Ibu.
Semua yang ada di situ terhenyak. Tiba-tiba seseorang begitu marah, mendorong Bapak sampai terjatuh. Para biksu membantu Bapak berdiri, tapi orang itu bertambah marah.
"Gara-gara kamu, beginilah keadaan Joys sekarang. Sekarang juga pergi dari sini, atau kubunuh kau sekarang juga!"
Bapak bergeming. Tetap berdiri tegak. Menatap Koh Sinyo kakak Ibuku.
"Kaulah yang mengambil Joys dari kami, hingga dia menjadi seperti ini," kata Bapak bergetar.
Lelaki bermata sipit di depan Bapak semakin beringas, dia mengambil pisau di sebelah patung Budha di kamar Ibu. Menusuk pinggang kanan Bapak. Tapi seorang Biksu menghalanginya.
Darah memancar, dari tangan Bapak dan Biksu itu. Dengan tangan yang masih berdarah, Bapak segera ditarik dan dipeluk, lalu dibawa berlari. Mereka terus berlari, sampai mereka berdua berada di vihara di pojok Pecinan.
Bapak hapal betul vihara itu. Dulu Bapak selalu menunggu Ibu saat Ibu sedang melakukan kebaktian, meditasi, belajar Dhamma dan berbagai kegiatan lainnya. Ibu pernah mengajak Bapak berkeliling vihara untuk melihat bangunan utamanya. Kata Ibu namanya dhammasal, yang digunakan untuk kebaktian, serta bangunan lain seperti uposathagara, untuk pentahbisan biksu, bhavana sabha untuk meditasi, dan kuthi, tempat tinggal biksu.
Biksu berwajah tenang, seusia lebih tua dari Bapak itu, membersihkan luka dan mengobati luka sayatan pisau di lengan Bapak. Bapak menangis perlahan.
"Menangislah Anakku. Kalau itu akan membuatmu lega, seperti istrimu Joys yang selalu menangis di sini. Ia juga selalu bercerita apa yang dirasakan selama ini. Tentangmu, tentang anakmu, tentang cintanya pada kalian yang begitu besar, juga tentang tekanan dan ancaman keluarganya untuk memisahkan kalian."
Dari Sang Biksu itulah mengalir cerita, bahwa saat Ibu datang ke vihara di sebuah pagi buta, keluarganya langsung membawa Ibu, tak menyisakan sedikitpun waktu untuk mengabari aku dan Bapak. Mereka memang sengaja mengambil Ibu dari kami. Ibu dikurung di rumah besar itu, sampai hari itu, hari dimana Bapak melihat Ibu dengan keadaan yang begitu menyedihkan.
"Luka batin karena kerinduannya yang teramat sangat denganmu dan anaknyalah yang membuatnya sakit seperti itu. Keluarganya memang sudah membawanya berobat kemanapun, tapi istrimu tak kunjung sembuh. Hingga ada salah satu keluarganya yang memohon kepada kami untuk melakukan doa kepadanya dalam tiap bulan, di hari yang sama seperti hari ini," kata Sang Biksu.
Sejak hari itulah, Bapak memangkas rambut gondrongnya habis. Dalam satu hari di setiap bulan, Bapak selalu menunggu di ujung jalan, untuk menunggu rombongan para Biksu itu lewat, Bapak atas ijin Biksu yang baik hati itu, lalu menyelinap di antara rombongan. Berpakaian sama seperti mereka. Berjalan dengan dada berdegup kencang, saat melewati lorong demi lorong rumah besar itu, menuju kamar Ibu.
Sesampai di kamar Ibu, tak ada satu pun yang tahu, bahwa ada Bapak di situ, kecuali Sang Biksu yang mengijinkan Bapak melakukan itu semua.
Bapak hanya cukup menatap Ibu, menggenggam tangan Ibu yang kusut dan kering. Menyebut namanya dalam hening dan pelan. Dan entah, sepertinya Ibu tahu, bahwa itu adalah Bapak. Ibu dengan mata terpejamnya, akan selalu meneteskan air mata, jika giliran Bapak tiba. Hanya berlangsung beberapa detik, tapi bagi Bapak, itulah hari terbaik sepanjang hidupnya. Hari yang selalu ia tunggu. Hari dimana ia bisa melihat Ibu, menggenggam tangannya, dan berdoa untuknya.
Seperti pagi ini, aku menatap Bapak dari kursi kayu ini. Melihat dari belakang punggungnya yang semakin kurus dan tubuhnya yang mulai membungkuk. Bapak di depan cermin, dengan mata yang selalu tiba-tiba menyala di pagi itu, memilih pengaturan yang sesuai dengan panjang rambut yang diinginkan. Kemudian, mulai mencukur dari bagian samping dan belakang kepala dengan gerakan searah pertumbuhan rambut. Bapak menggunakan ujung alat untuk merapikan bagian bawah dan samping kepalanya. "Ser...ser... ser...ser...," begitu suaranya. Seperti suara hatiku yang menyayat tiap Bapak melakukan itu. Tiap bulan, di setiap hari terbaiknya. Kuseka dengan cepat, air mataku yang turun sangat perlahan. Selalu begitu, di hari terbaik bapakku.(*)
--------------------------
PIPIEK ISFIANTI
Ia menulis cerpen, puisi dan juga naskah lakon. Seorang pekerja teater di Keluarga Segitiga Teater Kudus, Aktris Terbaik Festival Teater Mahasiswa 1994, salah satu Fasilitator Loka Pijar FTP Djarum 2025, tinggal di Kudus.


Lesung Jumengglung, karya Putut Pasopati