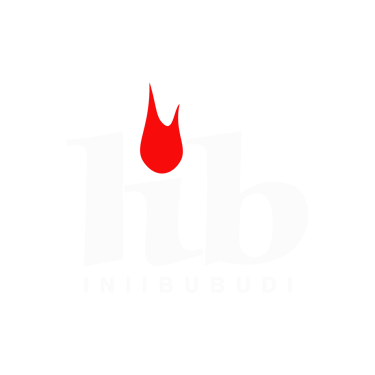Iman dan Puisi
ESAI
Oleh: Alexander Robert
12/1/2025
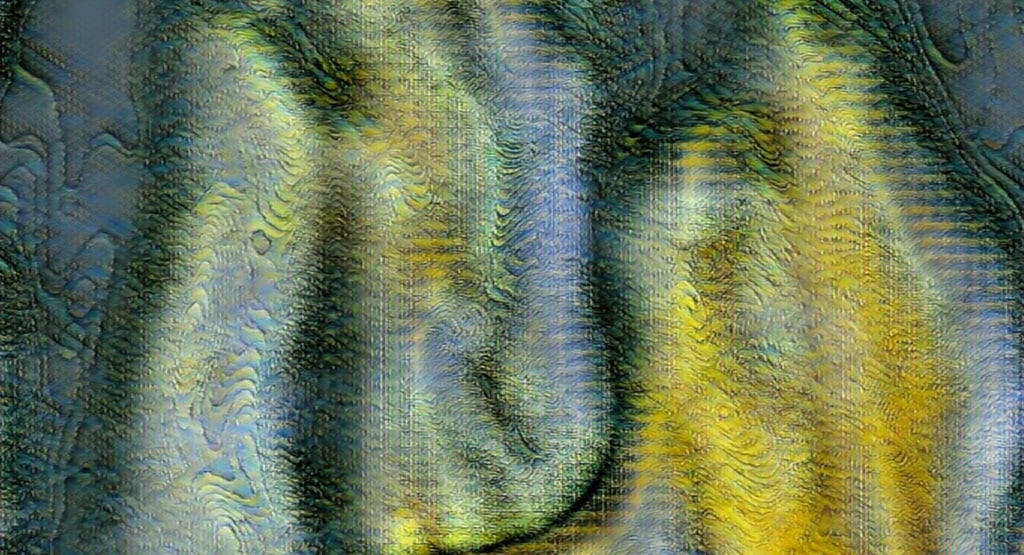

ADAKAH iman dalam puisi? Bagaimana puisi mengisahkan iman yang linear dengan nafas agama? Kata-kata yang tersusun dalam puisi, mulanya barangkali sekerjap metafor yang punya momen puitik dari penyair. Setidaknya ia, si penyair, telah menyaringnya hingga tandas, sampai ke akar kata lalu menuliskannya dalam puisi. Dan pada November 1943, Chairil Anwar menuliskan ”Doa”:
Tuhanku
Dalam termangu
Aku masih menyebut namaMu
Biar susah sungguh
Mengingat Kau penuh seluruh
CayaMu panas suci
Tinggal kerdip lilin di kelam sunyi
Tuhanku
Aku hilang bentuk
Remuk
Tuhanku
Aku mengembara di negeri asing
Tuhanku
Di pintumu aku mengetuk
Aku tidak bisa berpaling
Ini merupakan puisi dari Anwar yang romantis, bagaimana dirinya memasrahkan diri dengan penuh dan seluruh. Khidmat, hening, tak berdaya—hingga akhirnya kembali menyadari dirinya sendiri. Menyadari jika ia hanya sebatas hamba di hadapan Sang Pencipta. Di usianya yang masih muda, ia telah memikirkan kenyataan yang kelak akan dihadapinya (kematian).
Pun ihwal iman juga luruh dalam puisi Sapardi Djoko Damono, ia menelusuri ruang kreligiusannya sendiri. Sapardi kerap melakukan perenungan yang mendalam kepada Tuhan. Dengan cara, melakukan pengoyakan kecil terhadap dirinya sendiri. Dalam “Sajak Desember”, tercermin bagaimana ia mengungkapkan ketaklukannya sebagai insan yang paling kecil di semesta ini. Ia merasa dirinya begitu kecil dihadapan-Nya. Seperti yang pernah dilakukan Chairil Anwar, perkenankan saya mengutip sajak “Doa”-nya sebagian saja: Di pintu-Mu aku mengetuk/ aku tak bisa berpaling.
Oleh Sapardi, ia seperti menafsirkan waktu, seperti juga dalam sajaknya “Perihal Waktu”, dengan melakukan kutipan sedikit di mukanya, sebuah sajak dari T.S. Eliot: time present and time past/ are both perhaps present in time future,/ and time future was present in time past. Ketika tanggal-tanggal berganti, mendadak Sapardi merenung, betapa telah lama ia—barangkali juga kita telah kehilangan waktu. Bertambahnya usia setahun, sinonim dengan berkurangnya usia setahun, berkurangnya hidup di muka bumi ini selama setahun pula.waktu yang terus berjalan linier tanpa bisa dimundurkan layaknya arloji.
Begitu juga dalam “Surah Penghujan”—yang diberikan label ayat 1-24. Sapardi pun menggoda dengan religius. Menyaksikan remah-remah kehidupan yang sempat lewat dan tak pernah kita perhitungkan. Hal ini turut mengingatkan saya pada beberapa larik santun dalam puisi-puisi Taufiq Ismail. Berikut kutipannya:
(ayat 1)
musim harus berganti musim agar langit menjadi biru untuk kemudian kelabu agar air menguap untuk kemudian membeku agar pohon tumbuh untuk kemudian rubuh agar akar menyerap air untuk dikirim ke tunas daun untuk kemudian gugur agar lebah menyilangkan putik dan benang sari untuk kemudian layu agar rumput meriap untuk kemudian kering agar telur menetas dan burung terbang untuk kemudian patah sayapnya agar hari bergeser dari minggu ke sabtu agar kau mengingat untuk kemudian melupakan-Ku
agar kau tahu bahwa Aku melaksanakan kehendak-Ku
agar kau sadar bahwa aku memenuhi janji-Ku
Sebuah gumam yang religius. Menyimpan buah kesadaran yang dalam. Membangkitkan setiap keterjagaan kita, di antara keletihan dan prahara yang melilit. Sapardi mengangkat itu perlahan, membiarkannya jadi cair dan mendedahkannya dengan menyimpan setiap ingatan terhadap peristiwa yang pernah berlalu. Percikan memori yang begitu purba, mengingatkan bila sebenarnya kita terlampau kerdil untuk menerima segalanya.
Bahkan di pada puisi sebelumnya, sapardi juga menyitir perihal doa. Meskipun ia lebih memilih berbuat untuk orang lain melalui puisi “Dalam Doaku”:
dalam doaku subuh ini kau menjelma langit yang semalaman
tak memejamkan mata, yang meluas bening
siap menerima cahaya pertama, yang melengkung hening
karena akan menerima suara-suara
ketika matahari mengambang tenang di atas kepala, dalam
doaku kau menjelma pucuk-pucuk cemara
yang hijau senantiasa,
yang tak henti-hentinya mengajukan
pertanyaan muskil kepada angin yang mendesau
entah dari mana
dalam doaku sore ini kau menjelma seekor burung gereja
yang mengibas-ngibaskan bulunya dalam gerimis, yang
hinggap di ranting dan menggugurkan bulu-bulu bunga jambu,
yang tiba-tiba gelisah dan terbang lalu hinggap
di dahan pohon mangga itu
maghrib ini di dalam doaku
kau menjelma angin yang turun sangat pelahan dari nun di sana,
bersijingkat di jalan kecil itu, menyusup di celah-celah jendela dan pintu,
dan menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya di
rambut, dahi, dan bulu-bulu mataku
dalam doa malamku kau menjelma denyut jantungku, yang
dengan sabar bersitahan terhadap rasa sakit yang
entah batasnya, yang setia mengusut rahasia demi rahasia,
yang tak putus-putusnya bernyanyi
bagi kehidupanku
aku mencintaimu, itu sebabnya aku takkan pernah selesai
mendoakan keselamatanmu
Ihwal kepasrahan turut hadir dalam aku larik, ia hanya bisa menggumamkan atau sekadar melantunkan doa, selebihnya aku lirik kembali kepada Tuhan. Hanya ada “tangan” yang lebih kuasa dan menjaga dari tangannya sendiri. Sebuah puisi yang tertib dan turut mengamini sejumlah peristiwa di dalamnya: keselematan orang lain.
Hal berbeda yang ditawarkan oleh Joko Pinurbo, dengan rangkaian yang satir—ia menyentak dengan penuh sindiran melalui puisi “Doa Orang Sibuk Yang 24 Jam Sehari Berkantor Di Ponselnya”, Jokpin menulis:
Tuhan, ponsel saya
rusak dibanting gempa.
Nomor-nomor kontak saya hilang semua.
Satu-satunya yang tersisa
ialah nomorMu.
Tuhan berkata:
Dan itulah satu-satunya nomor
yang tak pernah kausapa.
Di sini Jokpin, seperti menghadapkan cermin ke seseorang, yang telah lama alpa dan lalai dengan mendestruksi kegagalan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Sebuah ponsel dengan pelbagai informasi “riuh” di dalam perangkatnya, justru menghadirkan ruang kosong tersendiri. Sosok Tuhan yang menjelma jadi ruang panggilan dari dalam hati, yang justru tak pernah dihubungi untuk sekadar berdoa (bercakap).
Ah, adakah iman dalam puisi? Setidaknya lewat kata-kata, puisi dengan formulanya yang ajaib acap memancarkan sebuah pencerahan. Mungkin, ia seperti tetes air di atas batu, perlahan dan pasti, menciptakan rongga cahaya lewat balutan metaforanya.(*)
--------------------------
ALEXANDER ROBERT
Alexander Robert Nainggolan (Alex R. Nainggolan) lahir di Jakarta, 16 Januari 1982. Bekerja sebagai staf Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPMPTSP) Kota Adm. Jakarta Barat. Menyelesaikan studi di FE Unila jurusan Manajemen. Tulisan berupa cerpen, puisi, esai, tinjauan buku terpublikasi di media cetak dan online. Bukunya yang telah terbit Rumah Malam di Mata Ibu (kumpulan cerpen, Penerbit Pensil 324 Jakarta, 2012), Sajak yang Tak Selesai (kumpulan puisi, Nulis Buku, 2012), Kitab Kemungkinan (kumpulan cerpen, Nulis Buku, 2012), Silsilah Kata (kumpulan puisi, Penerbit basabasi, 2016), Dua Pekan Kesunyian (kumpulan puisi, Penerbit JBS, 2023), Fragmen-fragmen bagi Sayyidina Muhammad (kumpulan puisi, Penerbit Diva Press, 2024).